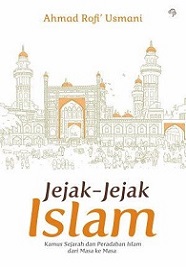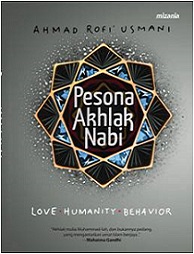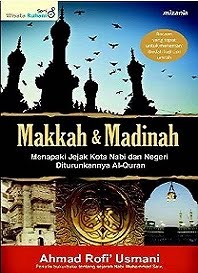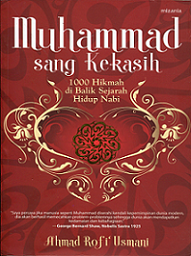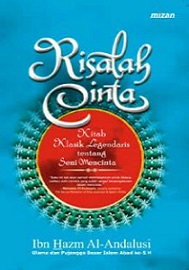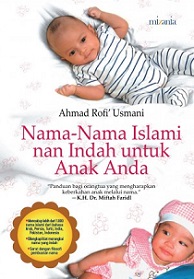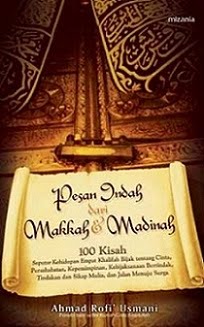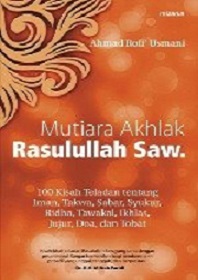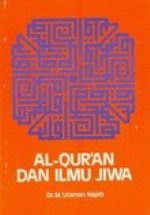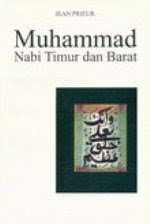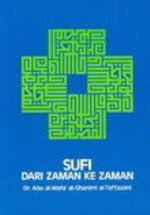“Ketika masih muda, di bulan Ramadhan, saya sering membaca puisi Goethe yang menyingkapkan doanya, yang begitu dalam, kepada Tuhan,” tulis seorang mantan Sekretaris Jenderal Organisasi Konferensi Islam yang juga mantan presiden. “Dalam puisi tersebut, Goethe tak pernah lupa bahwa ia hidup di Bumi, sedangkan ruhnya membubung tinggi di alam ketuhanan. Bukan luar biasa bila doanya begitu indah dan memancarkan cintanya yang begitu dalam kepada Tuhannya dan keterbuaiannya di dalam-Nya. Ucap Goethe:
Karuniailah aku kekuatan berpikir, duhai Tuhan
Biar kuhidup laksana singa
Karuniailah aku kehidupan nan sederhana dan damai, duhai Tuhan
Biar kudekati Engkau sepenuh cinta
Doa nan indah itu tidak mungkin timbul kecuali dari relung kalbu yang diwarnai iman. Kalbu yang begitu mencitarasai cinta ilahi. Juga merasa, tanpa cinta tersebut kehidupan tanpa makna. Kehidupan yang menyadari keimanan kepada Tuhan sebagai peringkat pengenalan (ma‘rifah) kepada-Nya yang paling dalam. Keimanan yang didasarkan pada cinta timbal balik, bukan didasarkan pada rasa gentar manusia terhadap kewibawaan Tuhan. Ketika cinta ilahi ini mewarnai kalbu seseorang, kekelaman yang ada pun menjadi sirna. Bagaikan meredupnya kegelapan di hadapan cahaya.
Merenungi cinta membuat saya teringat suatu peristiwa yang pernah saya alami ketika masih menjadi Pemimpin Redaksi koran Al-Jumhuriyyah. Suatu hari saya menulis sebuah tajuk dengan judul “Wawasan”. Dalam tajuk itu saya tulis, saya tidak pernah ingat kepada Allah kecuali dalam kedudukan-Nya sebagai Sahabat yang saya cintai dan tidak saya takuti. Sebab, pikiran yang sederhana pun akan menyatakan, adanya rasa cinta berlawanan sepenuhnya dengan adanya rasa takut. Jadi, bagaimana saya dapat mencintai Allah, sedangkan saya takut kepada-Nya?”
Siapakah presiden yang menggoreskan penanya untuk mengungkapkan tulisan di atas? Tak lain adalah Presiden Anwar Sadat, seorang presiden Mesir. Seperti diketahui, suami Jehan Sadat ini lahir pada Rabu, 21 Rabi‘ Al-Awwal 1337 H/25 Desember 1918 M, di Desa Mit Abu Al-Kum, di Provinsi Minufiyyah. Selepas lulus dari Akademi Militer ‘Abbasiyyah, Kairo, putra seorang pegawai negeri ini menjadi teman kental Nasser dan sejumlah perwira muda Mesir waktu itu kala ia ditempatkan di Manqabad, Mesir Selatan. Pada akhir tahun-tahun 1940-an, selama beberapa tahun, ia mendekam di penjara akibat kegiatannya yang anti pemerintah Mesir kala itu yang berada di bawah kendali Raja Faruq.

Di 1370 H/1950 M, sekeluarnya dari penjara, nama Sadat direhabilitasi. Sekitar dua tahun kemudian, tepatnya Rabu, 1 Dzul Qa‘dah 1371 H/23 Juli 1952 M, ia bersama “Kelompok Perwira Bebas” terlibat dalam kudeta terhadap Raja Faruq. Kariernya pun mulai menanjak, antara lain sebagai Menteri Negara, Ketua Majelis Nasional, editor koran Al-Jumhûriyyah, dan Wakil Presiden Mesir. Pada Senin, 27 Rajab 1390 H/28 September 1970 M ia diangkat sebagai Presiden Mesir, menggantikan Presiden Nasser yang meninggal dunia karena sakit jantung.
Selain sebagai presiden, Anwar Sadat ternyata juga seorang penulis. Karya tulisnya, antara lain, adalah
Al-Bahts ‘an Al-Dzât, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul
In Search of Excellence. Dan, beberapa lama selepas berpulang, sebuah bukunya berjudul
Washiyyatî (Pesanku) terbit. Selain menyatakan kekagumannya terhadap Jalaluddin Al-Rumi, Rabi‘ah Adawiyyah, Ibn ‘Arabi, Ibn Al-Faridh, dan Goethe, dalam karyanya tersebut ia juga mengemukakan pandangannya tentang cinta, persahabatan, dan hal-hal lainnya. Kini, marilah sejenak kita ikuti tulisan lanjut Anwar Sadat tersebut seperti diungkapkan dalam karya tersebut di atas sebagai berikut:
“Selepas terbitnya tajuk tersebut, timbul polemik keras tentang cinta kepada Allah. Ada yang mengatakan, rasa gentar merupakan bagian penting dari iman. Tapi, pengalaman saya tentang rasa takut menunjukkan, Allah tidak mungkin menjadi musuh yang menakutkan dan menggentarkan. Kecuali terhadap orang-orang yang mengingkari keberadaan dan kehadiran-Nya.
Betapa indah menjadikan Allah sebagai Sahabat dan Kekasih. Bila kita telah mencitarasai cinta ilahi ini dalam kehidupan kita, tiada sesuatu pun dalam alam ini bakal menghadang kita. Malah, kehidupan kita bakal berubah menjadi kebahagiaan yang hakiki. Allah telah menjadikan kebahagiaan di tangan kita sendiri, dipicu oleh cinta agung-Nya kepada kita. Tapi, manusia harus meraih kebahagiaan dengan tangannya sendiri. Dengan kata lain, segala sesuatu yang ada di sekitar kita tidak akan memberi kita kebahagiaan. Kita sendiri yang harus mengusahakannya. Dari sini dapat dikatakan, segala sesuatu dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia, selama sesuatu itu berada di tangannya. Dan, kehidupan di Bumi kita ini sejatinya merupakan kebahagiaan tanpa akhir. Bumi ini merupakan bagian semesta alam yang senantiasa menyampaikan puja dan puji kepada Allah. Di seluruh sisi kehidupan sejatinya terdapat kebahagiaan, baik pada kesehatan, keluarga, teman, kehidupan keluarga, kerja, renungan terhadap Allah, dan segala sesuatu lainnya.
Memahami semua itu, masih perlukah kita pada bukti lain tentang kecintaan Allah terhadap semesta alam ini? Jadi, wajar bila seseorang lebih mencintai Allah ketimbang yang selain-Nya, malah melebihi dirinya sendiri. Sebab, bila manusia merupakan bagian dari semesta alam, wajar bila sesuatu bagian dari keseluruhan tidak mungkin mencintai dirinya secara benar. Kecuali bila ia mencintai dirinya sebagai bagian dari keseluruhan tersebut. Dan, bukannya memandang diri sendiri sebagai pribadi yang terpisah dari keseluruhan dan mandiri. Manusia dalam kedudukannya sebagai makhluk yang berhutang kepada Allah dalam segala hal yang dimilikinya, tidak boleh tidak harus lebih mencintai Allah ketimbang dirinya sendiri. Dan, ia belum lagi mencintai-Nya selama ia belum merasa berasal dari-Nya.
Watak cinta yang matang dan dalam ialah cinta yang timbal balik dan tidak bertepuk sebelah tangan. Juga, pemicu cinta tersebut ialah keinginan untuk kembali kepada Allah. Cinta dalam pengertian ini membuat seluruh semesta alam sebagai ungkapan hidup cinta ilahi. Di sini, hubungan antara Khalik dan makhluk merupakan keharusan, demi kelangsungan pengertian alam yang sejatinya. Yaitu hubungan antara keseluruhan dengan bagian atau kesempurnaan Yang Mutlak dengan semesta alam yang kurang sempurna. Jadi, manusia belum lagi sempurna kemanusiaan dan keberadaannya kecuali bila menyadari cinta ilahi yang mewarnai dirinya dan seluruh semesta alam.
Pengertian cinta ilahi seperti itu, antara lain, dapat disingkapkan dari kisah Rabi‘ah Al-‘Adawiyyah, seorang sufi perempuan asal Bashrah yang hidup di abad ke-2 Hijriah. Suatu hari ia menaruh salah tangannya ke dalam api, dan tangannya yang satu lagi ke dalam air. Ketika ia ditanya mengapa melakukan tindakan demikian, ia menjawab, “
Api ini akan kulemparkan ke dalam surga. Sedangkan air ini akan kutuangkan ke dalam neraka. Sehingga, api dan air itu pun menjadi tiada, dan tersingkaplah kemudian, bagi para peniti jalan sufi, jalan menuju Allah dan tampak pulalah tujuan yang mereka titi. Mereka menjadi menyaksikan Allah tanpa rasa harap dan juga tanpa rasa gentar. Apakah bila rasa harap terhadap surga dan rasa gentar terhadap neraka tiada, tak akan ada seorang pun memuja-Nya?”
Maksud Rabi‘ah adalah cinta ilahi harus bebas dari pamrih dan keinginan diri. Ini lebih tampak lagi dalam munajatnya, “
Tuhanku! Bila aku menyembah-Mu karena takut neraka-Mu, biarkanlah diriku terbakar api neraka. Dan bila aku menyembah-Mu karena mengharap surga-Mu, jauhkanlah aku darinya. Tapi, bila aku menyembah-Mu hanya semata karena cinta kepada-Mu, Tuhanku, janganlah Kau-halangi melihat keindahan-Mu yang abadi.”
Itulah cinta yang hakiki. Menurut saya, seluruh kebaikan, kebenaran, dan keindahan di dunia tumbuh dari cinta tersebut.”
Demikianlah tulis presiden Mesir yang selama sebelas tahun menjadi orang nomor satu banyak peristiwa yang mewarnai masa pemerintahannya. Antara lain, pengusiran para penasehat militer Uni Soviet (1972), Perang 6 Oktober 1973, kunjungannya ke Israel (November 1977), dan Penjanjian Camp David (September 1978). Tiga tahun setelah ditandatanganinya perjanjian itu, tepatnya pada Selasa, 7 Dzul Hijjah 1401 H/6 Oktober 1981 M, ia tewas dalam peristiwa pembunuhan ketika sedang menghadiri parade militer dalam rangka memperingati Perang 6 Oktober.