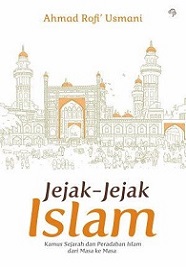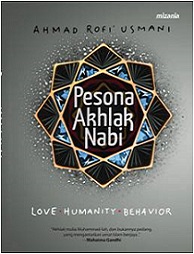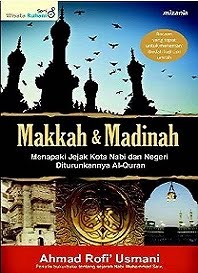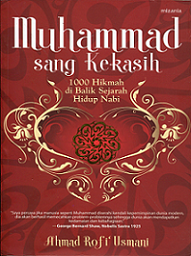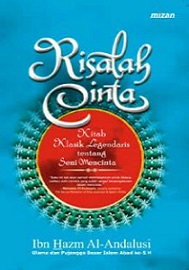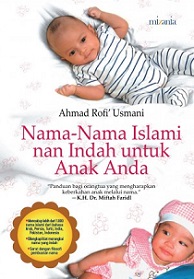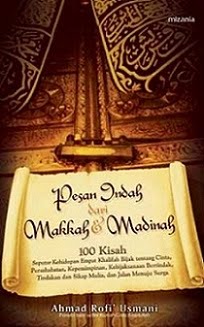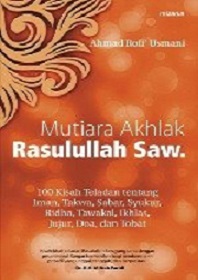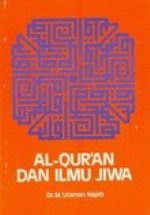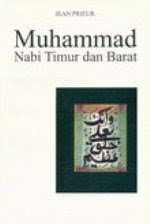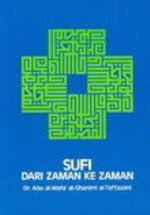PERTEMUAN (IMAJINER) DI KUBAH AL-SHAKHRAH, JERUSALEM
“Lo,
bukankah itu Gerbang Raja Herodes!”
Begitu
ucap bibir saya ketika saya mendapatkan diri saya tiba-tiba berdiri di
perempatan yang memisahkan antara Salah e-Din St. dan Sultan Suleiman St.,
Al-Quds alias Jerusalem. Hal itu terjadi dalam mimpi saya pada malam Senin, 9
Agustus 2015, dua hari yang lalu. Mimpi terlempar jauh, ke Jerusalem, Palestina
dalam tidur yang sangat pulas selepas menjadi sopir antara Jakarta – Bandung.
Waktu saat itu menunjuk sekitar pukul tiga dini hari. Suasana di sekitar
perempatan itu sepi sekali. Tidak ada orang yang lalu lalang. Satu orang pun
tidak ada. Tidak jauh dari gerbang itu sebuah panser warna putih milik polisi
Israel dan dihiasi bendera negara itu sedang bersiaga. Entah apa yang mau
dihadapinya.
Menyadari
berada tidak jauh dari Gerbang Raja Herodes, segera dalam benak saya
menggelegak keinginan untuk menapakkan kaki menuju Kubah Al-Shakhrah (Dome of
the Rock) dan Masjid Al-Aqsha. Dengan langkah pelan, saya pun segera memasuki
gerbang itu dan kemudian menelusuri labirin lorong-lorong kecil menuju Masjid
Al-Aqsha. Sepanjang perjalanan, saya tidak bertemu siapa pun. Ketika melintasi
Via Dolorosa, lorong yang dikatakan sebagai lorong yang dilintasi Nabi Isa a.s.
ketika memanggul salib, saya lama mencermati lingkungan itu dan merenung. Dan, kemudian,
selepas berjalan sekitar 20 menit, langkah-langkah saya pun kian mendekati
gerbang ke arah Kubah Al-Shakhrah dan Masjid Al-Aqsha.
Dari
jauh saya melihat, dua polisi Israel dengan menyandang senjata berdiri di depan
pintu. Mungkin karena melihat saya melangkah menuju ke arah mereka, mereka
tampak siaga penuh. Apalagi saat itu dini hari yang sepi sekali.
“Good
morning! Selamat pagi!” ucap saya kepada mereka berdua, begitu langkah kaki
saya kian dekat dengan pintu itu.
“Hi
man, where do you come from? Dari mana kau?” jawab salah seorang polisi
itu, dengan nada suara galak.
“From
Indonesia,” jawab saya. Santai dan percaya diri, karena beberapa kali saya
pernah melintasi pintu itu dan menghadapi pertanyaan serupa. Sepengetahuan
saya, password “Indonesia” cukup mujarab untuk “membuka pintu itu”.
“Okey,
come in. Masuk!”
Begitu
melintasi pintu itu, dua petugas keamanan Palestina segera menyegat saya dan
bertanya dengan ramah. Tentu saja dalam bahasa Arab, “Kamu dari mana?”
“Dari
Indonesia.”
“Ahlan
wa sahlan,” ucap dua petugas keamanan itu dan kemudian memeluk saya. “Silakan
masuk. Itu banyak orang Indonesia sedang berkumpul di Kubah Al-Shakhrah. Ada
seorang syeikh yang sedang memberikan khotbah?”
“Banyak
orang Indonesia di Kubah Al-Sakhrah? Khotbah?” gumam saya dalam hati. “Lo,
kok mereka dibolehkan berkumpul di dalam kubah itu?”
Mendengar
penjelasan dua petugas keamanan demikian, saya pun segera melangkah cepat
menuju kubah itu. Segera, dari kejauhan, mencuat sebuah bangunan persegi
delapan dan di puncak bangunan itu bertengger sebuah kubah besar berwarna
keemasan. Itulah Kubah Al-Sakhrah.
Kubah
Al-Sakhrah, apa itu?
Kubah
yang satu itu adalah sebuah kubah dalam lingkungan Masjid Al-Aqsha, Bait
Al-Maqdis. Catatan sejarah menorehkan, kubah
itu dibangun di bawah pengarahan dua arsitek asal Jerusalem, yaitu Raja’ bin Hayawah Al-Kindi dan
Yazid ibn Salam.
Kubah ini dapat dikatakan merupakan cikal bakal seni
Islami, yang tujuan dasarnya
untuk mengekspresikan akidah
yang terkandung dalam Al-Quran. Hal ini seperti tertampilkan pada
lokasi kubah tersebut,
struktur bangunannya, dimensi
dan proporsinya,
bentuk-bentuk yang terdapat padanya,
warna-warna yang menghiasinya, garis
besar luarnya, dan simfoni ruang dalamnya.
Ide
pendirian bangunan tersebut sebenarnya cukup menarik: ide untuk menampilkan
lokasi batu yang menjadi tempat awal perjalanan Mi‘raj yang dilakukan Nabi Muhammad
Saw. menuju Sidrah Al-Muntaha, serta untuk melindunginya dari terpaan sinar
matahari, hujan, dan hajaran perjalanan hari. Konon, ‘Umar ibn Al-Khaththablah
yang pertama kali mengemukakan ide untuk memelihara batu tersebut. Karena itu,
dia kemudian memerintahkan pendirian loteng dari kayu di atas batu tersebut.
Loteng tersebut tetap bertahan hingga ketika ‘Abdul Malik ibn Marwan
mengunjunginya. Penguasa Dinasti Umawiyyah, dengan pusat pemerintahannya di
Damaskus, Suriah itu kemudian memerintahkan untuk menggantinya dengan sebuah
bangunan artistik yang selaras dengan kedudukan batu tersebut dalam kalangan
kaum Muslim.
‘Abdul
Malik ibn Marwan mengawali pembangunan bangunan Kubah Al-Shakhrah pada 69
H/688-689 M. Pembangunan kubah ini baru rampung pada 72 H/691-692 M. Bangunan
kubah ini merupakan sebuah ruangan lapang yang terdiri dari delapan sisi. Di
atasnya terdapat sebuah kubah bundar yang indah yang tegak di atas struktur
dari kayu. Bangunan ini, baik dari dalam maupun luar, diplester. Bagian dalam
kubah dihiasi dengan ornamen-ornamen Byzantium yang sangat menawan, sedangkan
bagian luarnya diberi warna keemasan. Al-Shakhrah tegak di dalam bangunan yang
dikelilingi lingkaran bukaan dan tegak di atas lengkung-lengkung lancip serta berada di atas tiang-tiang dan
penyangga-penyangga dari pualam.
Begitu
sampai di bangunan yang berbentuk segi delapan bak kristal yang menggambarkan bumi, berlapis emas, dan
memiliki tinggi dan garis tengah sekitar 25
meter itu, saya pun segera menuju
pintu di sebelah kanan dari arah saya datang. Sebelum memasuki bangunan itu,
karena udara terasa dingin, sekitar 19 derajat celcius, saya pun menutupi muka
saya dengan kafiyeh. Dan, begitu
langkah saya menapaki bagian dalam bangunan, mâ syâa Allâh, saya melihat
banyak orang Indonesia sedang mendengarkan pengajian yang diberikan seseorang
yang duduk di atas kursi.
Begitu
mencermati mereka, betapa kaget saya. Orang yang memberikan pengajian itu,
ternyata, adalah seorang kiai kondang yang sangat saya kenal, KH Ali Maksum,
seorang mantan Rais Am PBNU. Dan, ternyata pula, orang-orang yang duduk di sebelah
kanan kiai yang ahli tafsir Al-Quran itu adalah sejumlah kiai, ilmuwan, dan
tokoh. Antara lain KH Abdul Hamid dari Pasuruan, seorang kiai yang terkenal
tawadhu’ dan Prof. Dr. A. Mukti Ali. Tampaknya, mereka adalah para kiai dan
pakaryang pernah menjadi sahabat dan murid menantu KH Munawwir, pendiri Pondok
Pesantren Krapyak, Yogyakarta itu ketika mereka menimba ilmu di Pesantren
Tremas, Pacitan, Jawa Timur.
Sementara
orang-orang yang duduk di depan kiai yang putra seorang kiai asal Lasem, Jawa
Tengah, saya lihat sejumlah kiai terkemuka dari seluruh penjuru Indonesia. Dan,
orang-orang yang duduk di sebelah kiri beliau adalah para petinggi dan tokoh
Nahdlatul Ulama yang pernah menimba ilmu di Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta.
Termasuk Gus Dur, Gus Mus, Muzammil Basyuni, Said Aqil Siraj, Yusuf Muhammad,
Masdar F. Mas’udi, Syihabuddin Qalyubi, Habib Syarif Muhammad, Yahya Cholil
Staquf, dan lain-lainnya.
Saya
pun diam-diam bergabung dengan kelompok terakhir itu. Tidak ingin mengganggu
pengajian yang sedang berlangsung, selepas mengucapkan salam dengan suara
pelan, saya pun duduk di belakang Masdar F. Mas’udi. Mâ syâa Allâh,
ternyata, KH Ali Maksum saat itu sedang memberikan pengajian tentang “Larangan
Mengangkat Pejabat yang Ambisius” dari Kitâb Riyâdh Al-Shâlihîn, karya
seorang ulama terkemuka abad ke-7 H/13 M, Imam Al-Nawawi: pengajian yang
memikat yang senantiasa saya ikuti selama lima kali bulan Ramadhan, ketika saya
masih menjadi santri di Pondok Pesantren Krapyak. Semua yang hadir begitu
khidmat mendengar pengajian yang disajikan dengan menawan dan sangat membuka
wawasan. Pengajian yang senantiasa saya rindukan hingga kini.
Usai
memberikan pengajian, tiba-tiba KH Ali Maksum mengarahkan pandangannya kepada
Gus Mus. Lantas, tanya beliau kepada putra KH Bisri Mustofa, Rembang itu dengan
nada penuh wibawa, “Mustofa! Kenapa kamu menolak tawaran untuk menjadi Rais Am
PBNU?”
“Nyuwun
sewu, Kiai. Mohon maaf, Kiai,” jawab Gus Mus dengan suara pelan dan gemetar
seraya menundukkan kepala. “Saya tidak pantas menduduki jabatan itu. Masih
banyak para kiai sepuh yang lebih layak dan pantas dari pada saya untuk
menduduki jabatan yang berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah Swt. kelak.
Bukankah tadi Kiai dengan indah menjelaskan, Rasulullah Saw. melarang kita
mengangkat pejabat yang ambisius. Saya khawatir, dalam hati saya ada sebutir
ambisi dan riya’ ketika menerima jabatan itu. Nyuwun sewu Kiai, saya
tidak kuasa menerima jabatan itu.”
“Benar
sikapmu itu. Meski kadang jiwa senimu mencuat, tapi kamu cukup bijak. Kiranya
Allah Swt. memberkahi sikap dan langkahmu, Mustofa.”
“Amîn
yâ Mujîb Al-Sâilîn, Kiai. Matur nuwun sanget, Kiai. Kersoho
Kiai senantiasa mendoakan saya.”
“In
syâa Allâh, saya akan selalu mendoakan kamu. Tapi, jangan lupa tetap
mendaras Kitâb Riyâdh Al-Shâlihîn.”
“Inggih,
Kiai.”
Usai
berbincang dengan Gus Mus, pandangan KH Ali Maksum kemudian terarah lama kepada
Said Aqil Siraj. Pandangan hadirin pun terarah pula kepada doktor lulusan
Universitas Umm Al-Qura, Makkah itu. Tak lama selepas itu, beliau berucap,
“Said! Saya tahu banyak tentang dirimu. Ayahmu, Kiai Aqil dari Kempek,
Palimanan dan KH Mahrus Lirboyo banyak bercerita tentang dirimu kepadaku. Saya
pun tahu, kamu cerdas, kuat membaca, dan memiliki wawasan yang luas. Namun,
saya lihat, kamu ini sedikit ambisius dan kurang hati-hati dalam berbicara
kepada masyarakat luas. Jagalah ucapanmu dan hati-hati setiap kali kamu
memberikan pernyataan. Kamu tampaknya lama tidak menyimak Kitâb Riyâdh
Al-Shâlihîn. Saya harapkan kamu, juga-juga para santri Pondok Pesantren
Krapyak yang lain, sering menyimak kembali karya besar Imam Al-Nawawi itu,
supaya kamu lebih tawadhu’ dan melakukan murâqabah dan muhâsabah.
Pintar tapi tidak tawadhu dan jarang melakukan murâqabah dan muhâsabah
akan membuat kamu sombong dan takabur.”
“Inggih,
Kiai,” jawab Said Aqil Siraj dengan suara pelan dan gemetar. “Nyuwun
pandonganipun Kiai, mugi kawulo mboten dados tiyang ingkang sombong lan takabur.”
“Ya,
seperti halnya Mustofa dan murid-muridku yang lain, selalu saya doakan, kiranya
kalian semua tidak menjadi orang yang sombong dan takabur.”
Rampung
berbicara dengan Said Aqil Siraj, pandangan KH Ali Maksum kemudian terarah
kepada Masdar F. Mas’udi. Pandangan hadirin pun terarah pula kiai asal Ajibarang,
Banyumas itu. KH Ali Maksum itu kemudian berucap kepada Masdar F. Mas’udi,
“Masdar! Seperti halnya Said, kamu juga cerdas, memiliki bacaan yang luas, dan
berwawasan luas. Kamu pun berani memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda.
Tapi, saya juga meminta kamu untuk lebih berhati-hati dalam berpendapat.
Bacalah kembali, sesering yang dapat kamu lakukan, Kitâb Riyâdh Al-Shâlihîn.
Biar kalbu dan benakmu kian lembut dan tawadhu’. Saya masih percaya denganmu.”
“Inggih,
Kiai. Kadang, saya sempat menyimak kitab itu. Matur nuwun, Kiai sampun kerso
paring nasihat dateng kawulo.”
Usai
berucap demikian, KH Ali Maksum kemudian mengarahkan pandangan beliau kepada
hadirin. Tak lama kemudian, beliau berucap, “Hadirin yang saya muliakan. Dini
hari ini saya sengaja mengajak hadirin semua ke tempat ini, tempat yang pernah
menjadi saksi kehadiran Rasulullah Saw. sebelum menghadap kepada Allah Swt. di
Sidrah Al-Muntaha, dalam Peristiwa Mi‘raj, dengan tujuan supaya kita kembali
menyimak dan meneladani teladan yang digariskan Rasulullah Saw. Karena itu,
saya tadi sengaja memberikan pengajian Kitâb Riyâdh Al-Shâlihîn. Tentu,
hadirin semua mengetahui, karya besar Imam Muhyiddin Abu Zakariyya
Yahya bin Syaraf bin Murri
bin Hasan bin Husain
bin Hizam bin Muhammad bin Jum‘ah Al-Nawawi
Al-Syafi‘i, yang berisi hadis-hadis pilihan, itu sarat dengan ajaran indah dari
Rasulullah Saw. Dan, sebentar lagi shalat Subuh akan tiba. Mari kita bersama
kita menuju ke Masjid Qibli (Masjid Al-Aqsha) di depan itu, untuk melaksanakan
shalat Shubuh berjamaah di situ.”
Benar,
tidak lama kemudian azan yang indah pun dilantunkan. Ternyata, azan tersebut
tidak dilantunkan dari masjid dengan empat menara di Bait Al-Maqdis itu. Tapi,
dari sebuah masjid dari dekat rumah saya di Baleendah, Kabupaten Bandung.
Mendengar azan tersebut, saya pun terbangun dari tidur pulas. Dan, semua yang saya
alami itu ternyata hanya mimpi belaka! Duh.