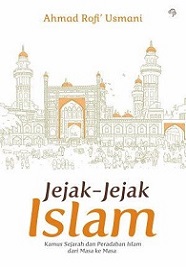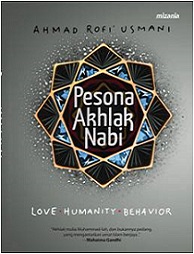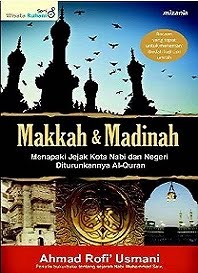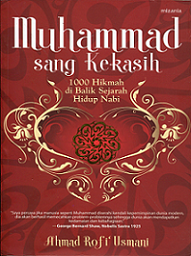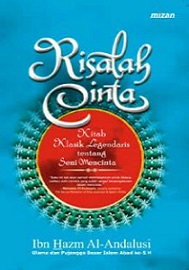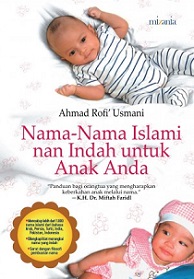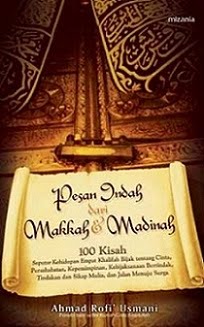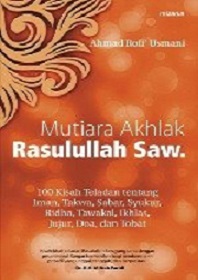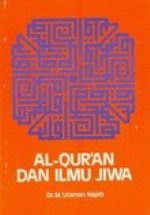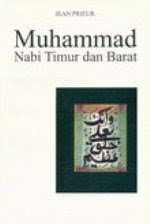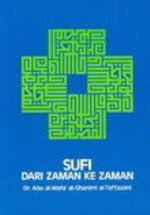Sakit Gigi dan Syaikh 'Abdul Qadir Al-Jailani
“Duh, ini mesti ada gigi yang lubang,” gumam
pelan bibir saya pada dini hari Rabu, 16 April 2014, yang lalu, sambil memegang
pipi kiri yang agak bengkak dan kepala terasa sangat nyeri. Meski menahan
sakit, karena dini hari itu telah berjanji akan mengantarkan istri ke Bandara
Husain Sastranegara, Bandung, saya pun segera bangkit dari tempat tidur. Dan,
sepanjang perjalanan dari rumah menuju bandara, saya tidak banyak menceritakan
sakit gigi itu kepada istri yang akan mengikuti simposium medis di Denpasar,
Bali. Selepas istri berangkat, dan saya kembali ke rumah di Baleendah, nyeri
karena sakit gigi itu kian “membara”. Segera, saya memberitahu istri yang
kemudian memberikan resep obat harus segera saya beli dan obat itu kemudian
saya minum.
Entah kenapa, ketika sedang menahan rasa sakit
tersebut, tiba-tiba benak saya “melayang-layang” jauh, Ya, melayang-layang jauh
ke Baghdad, Irak, karena teringat pesan indah seorang sufi terkemuka bernama
Syaikh ‘Abdul Qadir Al-Jailani. Sejak kecil, saya sejatinya sudah akrab dengan
nama sufi terkemuka tersebut, karena ayah saya adalah seorang kiai yang
pengikut Tarikat Qadiriyah-Naqsyabandiyah. Apa pesan sang sufi berkenaan dengan
sakit yang hari itu sedang saya “nikmati”? “Orang yang sakit,” demikian pesan
sang sufi, “adalah tamu Allah selama dia sakit. Setiap hari saat sakit, Allah
Swt. mengaruniakan kepadanya pahala yang tidak terhitung, selama dia
mengucapkan alhamdulillah (segala puja dan puji bagi Allah Swt. semata) dan
tidak melawan serta mengeluh. Dan, ketika Allah memulihkan kesehatannya, Dia
menghapus dosa-dosanya dan memberinya status seperti bayi yang baru lahir.
Sakit adalah pengampunan dan berkah.”
Teringat pesan indah yang demikian, sakit gigi
tersebut pun saya “nikmati” dengan ikhlas. Dan, kini, siapakah jati diri Syaikh ‘Abdul
Qadir Al-Jailani tersebut?
Bernama lengkap Abu Muhammad
Muhyiddin ‘Abdul Qadir bin Musa
bin ‘Abdullah Al-Jailani, pendiri Tarikat Qadiriyyah
ini lahir di Desa Nif atau
Naif, Jailan, selatan Laut Kaspia (kini masuk wilayah Iran), pada Ahad,
1 Ramadhan 470 H/18 Maret 1078 M. Selepas menimba ilmu di kota kelahirannya, pada 488 H/1095 M ia
dikirim ibundanya, Fathimah bin ‘Abdullah
Al-Shauma‘i, ke Baghdad. Di kota terakhir ini ia menimba ilmu dari sejumlah
tokoh ilmuwan dan ulama dan menempuh jalan
sufi. Ia belajar ilmu fikih kepada Syaikh Abu Al-Wafa’
dan Syaikh Abu Al-Khaththab Al-Kalwazani. Sedangkan di
bidang tasawuf ia menimba ilmu kepada Syaikh Abu Al-Khair Muhammad bin Muslim
Al-Dabbas dan Abu Sa‘d Mubarak Al-Mukharrimi dan di
bidang bahasa Arab kepada Abu Al-Husain Abu Ya‘la.
Di samping
menimba ilmu, Syaikh
‘Abdul Qadir Al-Jailani
juga acap melakukan pengembaraan. Antara lain, ke Persia, Mesir, dan
Semenanjung Arab. Tetapi, akhirnya
ia memilih Baghdad
sebagai tempat menetapnya. Di
kota itu, ia mendirikan
padepokan bagi murid-muridnya dan para sufi. Tasawuf, menurut ia,
adalah kebeningan dan kebersihan dari kotoran jiwa dan hawa
nafsu, hubungan yang benar dengan Allah dan akhlak yang mulia
dalam hubungan dengan sesama makhluk.
Semua itu agar tasawuf benar-benar selaras dengan syariah, hingga menjadi dasar
dalam hubungan antara sesama mereka
dan dalam hubungan
ibadah kepada Allah. Dengan
kata lain, tasawuf harus selaras
dengan Al-Quran dan Sunnah.
Dengan pandangannya yang demikian ini, tak aneh
bila Syaikh ‘Abdul Qadir Al-Jailani dikenal sebagai
sufi yang memiliki toleransi
yang tinggi dan sangat
menghormati tetangga, menjauhi kemewahan, dan kenikmatan duniawi. Ini tercermin, misalnya,
pada ucapannya, “Bukalah mata
jasmani dan mata hatimu lebar-lebar
terhadap dunia yang senantiasa mengecoh. Hadapilah
dengan meniadakan hawa
nafsu, tidak membiarkan ajakannya dan bawalah ke arah pengabdian
diri kepada Allah semata.”
Karena itu, tak aneh bila ia berpendapat
bahwa orang harus ditempa
dalam kesengsaraan agar mampu
merengkuh kedamaian batin. Allah Yang Maha Kuasa, menurutnya, menghadapkan orang-orang pilihan-Nya pada berbagai cobaan dan godaan,
untuk menguji kekuatan iman
mereka dan mengangkat
mereka secara ruhaniah dan moral.
Selain sebagai
sufi, Syaikh 'Abdul Qadir Al-Jailani juga
seorang faqîh yang mengikuti Mazhab Hanbali dan menguasai ushul fikih
dan fikih. Tak aneh bila ia mengaitkan tasawuf
dengan Al-Quran dan Sunnah.
Karenanya ia mendapat
pujian dari seorang
pengkritik keras tasawuf, Ibn Taimiyyah. Di samping itu, ia juga
terkenal sebagai seorang sufi
yang selalu memberikan
pengarahan kepada para muridnya
untuk senantiasa takut dan patuh
kepada Allah. Misalnya, suatu kala ia dimintai nasihat oleh
seorang muridnya tentang hal yang
menyebabkan iman dan agama rusak. Jawab Syaikh ‘Abdul Qadir
Al-Jailani, “Agamamu bisa sirna oleh empat hal: engkau tidak mau beramal
terhadap sesuatu yang tidak engkau ketahui, engkau tidak mau
belajar terhadap sesuatu yang
tidak engkau ketahui, engkau lakukan pekerjaan
atas dasar sesuatu yang tidak engkau ketahui, dan engkau menghalangi
orang untuk belajar sesuatu yang
tidak mereka ketahui.”
Sufi yang satu
ini menghadap Sang Pencipta di Baghdad pada Senin, 11 Rabi‘
Al-Akhir 561 H/14 Februari 1166 M,
dengan meninggalkan sejumlah karya. Antara lain Futûh Al-Ghaib
dan Al-Fuyudhât Al-Rabbâniyyah.