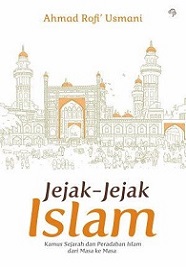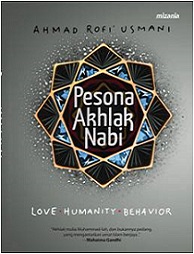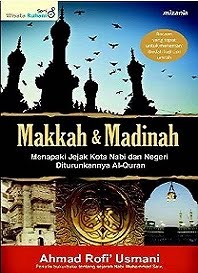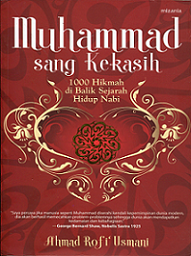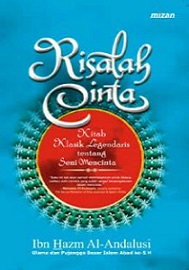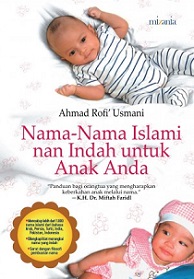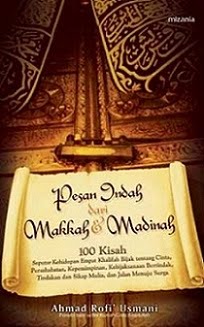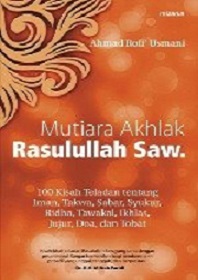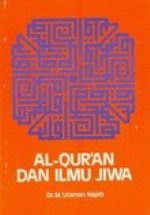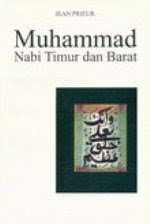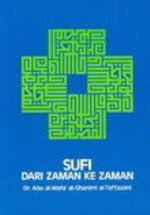MURIDKU, LAKSANAKAN HAJIMU SEKALI
LAGI!
Entah kenapa,
melihat beberapa sahabat dan kerabat saya pulang dari naik haji, tiba-tiba saya
teringat perbincangan menawan seorang sufi terkemuka, Abu Bakar Dulaf bin
Jahdar (Ja‘far bin Yunus) Al-Syibli dengan salah seorang muridnya yang belum
lama usai naik haji. Tentu saja, perbincangan mereka berdua berkisar di seputar
haji dan hikmah yang terkandung dalam ibadah tersebut.
“Indah sekali
pesan yang terkandung dalam perbincangan itu!”
Demikian gumam
bibir saya selepas merenungkan perbincangan panjang tersebut. Kini, bila Anda
berkenan, silakan simak perbincangan panjang menawan tersebut:
Suatu hari
salah seorang murid sang sufi asal Khurasan tersebut menemuinya selepas naik
haji. Usai berbagi sapa, sang sufi yang pernah menjadi Gubernur Demavend itu
bertanya pelan kepada si murid, “Muridku, apakah engkau telah menyiapkan niat
yang betul ketika engkau akan naik haji?”
“Sudah, Tuan
Guru. Saya telah menyiapkan niat yang betul ketika naik haji.”
“Bersama dengan
niat untuk naik haji, apakah engkau juga mempunyai niat untuk meninggalkan
selamanya segala hal yang telah engkau lakukan sejak engkau dilahirkan yang
bertentangan dengan semangat haji?”
“Tidak, Tuan
Guru. Tidak saya lakukan.”
“Duh, muridku.
Sejatinya dalam hal ini engkau tidak menyiapkan niat yang betul untuk naik
haji.” Usai berucap demikian, kemudian sang sufi berucap, “Ketika mengenakan
pakaian ihram, apakah engkau tanggalkan pakaianmu?”
“Ya, Tuan
Guru.”
“Pada saat
engkau tanggalkan pakaianmu, apakah engkau berjanji akan menanggalkan segala
sesuatu darimu selain Allah Swt.?”
“Oh, saya tidak
melakukannya, Tuan Guru.”
“Duh, muridku.
Dalam hal demikian sejatinya engkau tidak menanggalkan pakaianmu. Apakah engkau
membersihkan diri dengan mandi dan berwudhu?”
“Ya, saya
membersihkan diri dengan cara demikian.”
“Pada saat
itu, apakah engkau juga menjadi bersih dari segala dosa dan kesalahan?”
“Tidak.
Mengenai hal itu, saya merasa tidak pasti.”
“Duh, muridku.
Sejatinya dalam hal ini engkau tidak membersihkan dirimu. Apakah engkau
mengucapkan, ‘labbaika...’?”
“Ya, saya
mengucapkan, ‘labbaika...’”
“Apakah ketika
mengucapkan ‘labbaika...’ engkau mendengar jawabannya dari Allah Swt.?”
“Tidak, Tuan
Guru. Saya tidak mendengar jawaban apa pun.”
“Jika
demikian, talbiyah macam apa yang engkau ucapkan? Dan, (ketika melaksanakan
haji), apakah engkau memasuki Tanah Haram?”
“Ya, Tuan
Guru. Saya memasuki Tanah Haram.”
“Ketika engkau
memasuki Tanah Haram, apakah engkau berjanji akan meninggalkan setiap
yang haram. Untuk selamanya?”
“Tidak, Tuan
Guru. Saya tidak melakukannya.”
“Duh, muridku.
Sejatinya engkau tidak memasuki sama sekali Tanah Haram. Apakah engkau
berziarah ke Makkah?”
“Ya, saya
berziarah ke Kota Suci itu.”
“Ketika engkau
berziarah ke sana, apakah engkau melihat akhirat?”
“Tidak, Tuan
Guru. Saya tidak melihat apa pun.”
“Duh, muridku.
Sejatinya engkau tidak berziarah ke sana. Apakah engkau juga memasuki Masjid
Al-Haram?”
“Ya, saya
memasuki Masjid Al-Haram, Tuan Guru.”
“Ketika engkau
memasuki Masjid Al-Haram, apakah engkau merasakan dirimu dekat dengan
Allah Swt.?”
“Tidak, Tuan Guru.
Saya tidak merasakan apa pun.”
“Duh, muridku.
Sejatinya engkau tidak memasuki masjid itu. Apakah engkau melihat Ka‘bah?”
“Ya, Tuan
Guru. Saya melihatnya.”
“Apakah engkau
melihat Yang Wujud yang karena Dia Ka‘bah diziarahi.”
“Tidak, Tuan
Guru. Saya tidak melihat apa pun.”
“Duh, muridku.
Sejatinya engkau tidak melihat Ka‘bah. Apakah engkau melakukan raml
(lari kecil) ketika melaksanakan tawaf?”
“Ya, Tuan
Guru.”
“Ketika engkau
berlari kecil demikian, apakah engkau merasa dirimu ingin keluar dari urusan duniawi?”
“Tidak, Tuan
Guru.”
“Duh, muridku.
Sejatinya, dalam hal ini engkau tidak melakukan raml. Apakah engkau
letakkan tanganmu pada Hajar Aswad dan mengecupnya?”
“Ya, Tuan
Guru.”
Mendengar
jawaban muridnya yang demikian, tiba-tiba wajah sahabat seorang sufi terkemuka
asal Baghdad, Al-Junaid, itu memucat dan tubuhnya bergetar karena takut sekali.
Sehingga, jeritan kecil terlepas dari mulutnya. Beberapa lama kemudian tokoh
yang berpulang pada 334 H/846 M itu
berucap, “Celakalah engkau. Rasulullah Saw. berpesan, ‘Barang siapa
meletakkan tangannya di atas Hajar Aswad, dia bagaikan sedang berjabat
tangan dengan Allah Swt. Dia akan selamat dari segala-galanya.’ Apakah
engkau merasakan sesuatu dari keselamatan itu?”
“Tidak, Tuan
Guru. Saya tidak merasakan apa pun.”
“Duh.
Sejatinya engkau tidak menyentuh Hajar
Aswad, muridku. Apakah engkau melaksanakan shalat dua rakaat di dekat
Maqam Ibrahim?”
“Ya, Tuan
Guru. Saya melaksanakan shalat dua rakaat di tempat itu.”
“Suatu ketika
engkau akan ditempatkan di suatu tempat yang tinggi oleh Allah Swt. Apakah
engkau ketika itu merasa sedang melaksanakan urusan tersebut dengan kedudukan
yang tinggi yang mendorong engkau berdiri di situ?”
“Tidak, Tuan
Guru. Saya tidak melakukan apa pun.”
“Duh, muridku.
Sejatinya engkau tidak melaksanakan shalat dua rakaat di Maqam Ibrahim. Apakah
engkau melaksanakan sa‘i di antara Shafa dan Marwah serta mendaki Shafa?”
“Ya, Tuan
Guru.”
“Apakah yang
engkau lakukan di sana?”
“Saya
melantunkan takbir tiga kali dan berdoa kepada Allah Swt. agar menerima haji
saya.”
“Apakah para
malaikat juga melantunkan takbir bersamamu? Dan, apakah engkau memahami
pengertian takbir?”
“Tidak, Tuan
Guru.”
“Duh, muridku.
Sejatinya engkau tidak melantunkan takbir. Apakah engkau turun dari Shafa?”
“Ya, Tuan
Guru.”
“Ketika engkau
turun dari bukit tersebut, apakah engkau merasa bahwa segala kemaksiatan dan
kelemahan lepas dari dirimu serta kebeningan jiwa merasuki dirimu?”
“Tidak, Tuan
Guru.”
“Duh, muridku.
Sejatinya engkau tidak turun dari Shafa. Apakah engkau berlari kecil antara Shafa dan Marwah?”
“Ya, Tuan
Guru.”
“Ketika
berlari kecil, apakah engkau merasa dirimu melarikan diri jauh dari segala
sesuatu selain Allah Swt. dan sampai kepada-Nya?”
“Tidak, Tuan
Guru.”
“Jika demikian,
engkau tidak berlari kecil. Apakah engkau mendaki Marwah?”
“Ya, Tuan
Guru.”
“Ketika berada
di Marwah, apakah engkau merasakan ketenangan jiwa dan kedamaian yang
dikaruniakan kepadamu?”
“Tidak, Tuan
Guru.”
“Duh, muridku.
Sejatinya engkau tidak mendaki Marwah. Tuturkan kepadaku, apakah engkau
meneruskan perjalanan menuju Mina?”
“Ya, saya
melakukannya.”
“Ketika
berada di Mina, apakah engkau
mendambakan harapan kepada Allah Swt. bahwa engkau tidak akan melakukan
kemaksiatan?”
“Tidak, Tuan
Guru.”
“Hal itu
berarti engkau tidak pergi ke Mina. Apakah engkau berziarah ke Masjid Khaif?”
“Ya, Tuan
Guru.”
“Apakah
mengalami ketakutan kepada Allah Swt. yang belum pernah engkau alami
sebelumnya?”
“Tidak, Tuan
Guru.”
“Hal itu
berarti engkau tidak berziarah ke Masjid Khaif. Apakah engkau sampai ke
‘Arafah?”
“Ya, Tuan
Guru.”
“Ketika berada
di ‘Arafah, apakah engkau tahu, apakah sebab kehadiranmu di dunia ini, apa yang
engkau lakukan di sini, ke mana engkau akan pergi selepas ini, dan apakah tahu
hal-hal yang menunjukkan ke arah semua itu?”
“Tidak, Tuan
Guru.”
“Duh, muridku.
Dengan demikian, sejatinya engkau tidak mendatangi ‘Arafah. Apakah engkau
mendatangi Muzdalifah?”
“Ya, Tuan
Guru.”
“Ketika berada
di Muzdalifah, apakah engkau mengingat Allah, sehingga segala sesuatu engkau
lupakan ketika nama Allah Swt. disebut? (Hal ini merujuk pada firman Allah
Swt.,
“Tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari karunia (rezeki hasil
perniagaan) dari Tuhan kalian. Karena itu, apabila kalian telah bertolak dari
´Arafah, berdzikirlah kepada Allah di Masy´ar Al-Haram. Dan berdzikirlah
(dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepada kalian; dan
sesungguhnya kalian sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.” (QS Al-Baqarah [2]: 198))
“Tidak, Tuan Guru.”
“Dengan demikian, sejatinya
engkau tidak sampai ke Muzdalifah. Apakah engkau melaksanakan korban di Mina?”
“Ya, Tuan Guru.”
“Apakah engkau mengorbankan
dirimu?”
“Tidak, Tuan Guru.”
“Jadi, engkau tidak berkorban
apa pun. Apakah engkau melontar jamarat?”
“Ya, Tuan Guru.”
“Ketika engkau melontar
jamarat, apakah engkau merasakan dirimu melontar segala kebodohanmu dan merasa
ilmu pengetahuanmu bertambah?”
“Tidak, Tuan Guru.”
“Duh, muridku. Sejatinya engkau
tidak melontar jamarat. Apakah engkau melakukan ziarah?”
“Ya, Tuan Guru.”
“Apakah engkau merasakan
terjadinya peningkatan ruhaniahmu dan turunnya penghormatan serta kemuliaan
dari Allah Swt. kepadamu? Karena Rasulullah Saw. berpesan, ‘Barang siapa
melaksanakan haji atau barang siapa melaksanakan umrah, dia menjadi tamu Allah’,
dan manakala dia berziarah kepada seseorang, merupakan haknya untuk dihormati.”
“Tidak, Tuan Guru. Saya tidak
merasakan apa pun.”
“Duh, muridku. Sejatinya engkau
tidak melakukan ziarah apa pun. Apakah engkau kemudian menanggalkan kain ihram
yang engkau kenakan dengan tahallul?
“Ya, Tuan Guru.”
“Ketika engkau menanggalkan
kain ihram, apakah engkau berjanji akan mencari nafkah yang halal sepanjang
masa?”
“Tidak, Tuan Guru.”
“Duh, muridku. Sejatinya,
dengan demikian, engkau tidak menjadi halal (menanggalkan kain ihram). Apakah
engkau melakukan Tawaf Wada‘?”
“Ya, Tuan Guru.”
“Apakah engkau juga menyatakan
selamat tinggal sepenuhnya kepada hawa nafsumu?”
“Tidak, Tuan Guru.”
“Duh, muridku. Sejatinya engkau
tidak melakukan Tawaf Wada‘. Kembalilah ke Tanah Suci. Laksanakan hajimu sekali
lagi. Laksanakanlah sebagaimana telah kupaparkan kepadamu.”
Kisah yang indah dan sarat
dengan pesan. Kiranya kita semua dapat menjadikan kisah indah tersebut sebagai
renungan dan pelajaran.
Semoga!