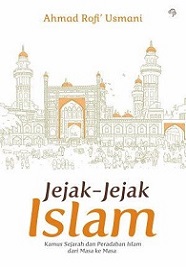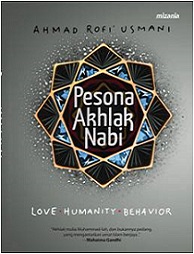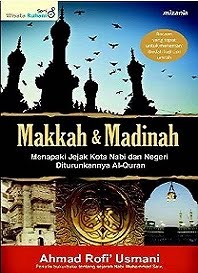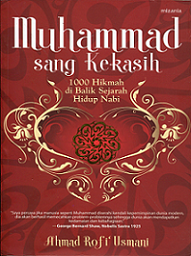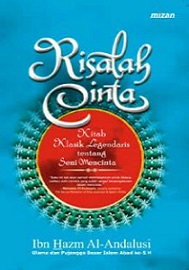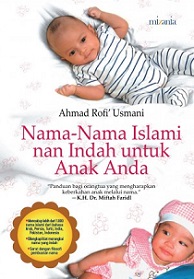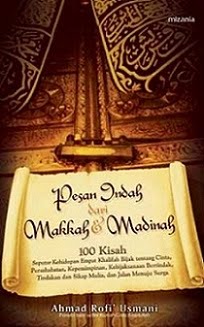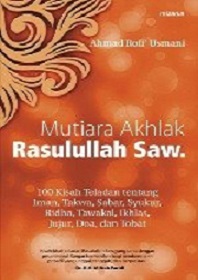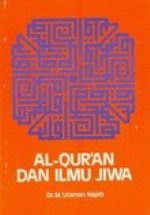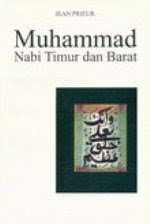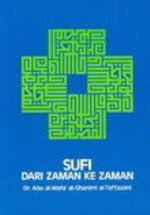“Ibn Baththuthah, betapa jauh nian jarak yang engkau tempuh dalam petualanganmu,” gumam penulis ketika sedang membaca sebuah karya tentang pengelana yang satu itu. Entah kenapa, saat ini penulis sedang “menggemari” pelbagai karya yang berkaitan dengan tokoh asal Maroko itu. Satu demi satu, pelbagai karya tentang tokoh berdarah Berber itu mulai berada di tangan.
Kini, bagaimanakah sejatinya kisah petualangan tokoh yang satu ini: kisah perjalanan yang menyita sekitar seperempat abad dari usianya, suatu perjalanan luar biasa, hingga untuk ukuran dewasa ini sekalipun?
“Pada 750 H/1349 M,” demikian tutur Douglas Bullis dan Norman MacDonald dalam tulisannya “From Pilgrim to World Traveler” (Saudi Aramco World, Juli/Agustus, 2000), “seorang penunggang kuda berpakaian lusuh dan berusia tengah baya berjalan pelan menuju Kota Tangier, yang terletak di sebuah pantai Afrika Utara. Ketika ia meninggalkan kota kelahirannya, Tangier, 24 tahun sebelumnya (pada masa pemerintahan Dinasti Mariniyyah), ia tak pernah merancang akan melakukan perjalanan yang ternyata kemudian “memakan” masa mudanya hingga ia memasuki usia tengah baya baru kembali ke kota kelahirannya itu. Ya, seperempat abad hidupnya berlangsung dalam petualangan. Dan, selama itu, sekalipun ia tak pernah menengok bumi kelahirannya!
Ketika kedua mata pria tengah baya itu menatap kota kelahirannya, tokoh yang lahir pada Senin, 17 Rajab 703 H/ 24 Februari l304 M dengan nama lengkap Syamsuddin Abu ‘Abdullah Muhammad bin ‘Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim bin Yusuf Al-Lawati Al-Thanji dan lebih terkenal dengan Ibn Baththuthah itu pun segera mencermati, satu demi satu, rumah-rumah yang menempati suatu lokasi melengkung sepanjang tepi Lautan Atlantik. Kala itu, ia mencoba “menampilkan kembali” seluruh rekaman kota yang telah ia tinggalkan semenjak sekitar seperempat abad sebelumnya. Segera, kenangannya ketika ia memulai kelana panjangnya pun muncul dalam benaknya.”
Pada 725 H/1325 M, kala baru berusia sekitar 21 tahun, anak muda berdarah Berber itu dengan perasaan enggan meninggalkan kedua orang tuanya, dengan bekal seekor kuda, uang, dan kain ihram, dengan tujuan untuk naik haji ke Makkah lewat jalan darat. Kota Suci itu berjarak sekitar 5.000 kilometer dari kota kelahirannya. Wajar, bila ia merasa gamang, karena merasa ia belum tentu bisa kembali lagi ke bumi kelahirannya. Berdasarkan penuturan jiran-jirannya yang pernah naik haji sebelumnya, perjalanan antara Tangier dan Makkah kala itu bukanlah perjalanan yang ringan dan aman. Apalagi, perjalanannya ke Makkah itu merupakan awal perjalanannya menempuh jarak ribuan kilometer. Dimulai dari Tangier, Maroko, lantas menuju Damaskus, dan kemudian Madinah hingga ke Makkah. Medan yang ia lintasi kala itu pun cukup berbahaya dan rawan gangguan keamanan, seperti melintasi gurun sahara, pegunungan, dan Sungai Nil.
Ternyata, rasa takut Ibn Baththuthah terbukti. Ketika sedang di tengah-tengah perjalanan di gurun pasir, ia pernah bersua dengan sekelompok perampok. Malah, ia sempat berkelahi dengan kawanan perampok itu. Akibatnya, anak Maroko itu nyaris dibunuh kawanan perampok itu. Untung, ia mendapatkan pertolongan dari salah seorang pimpinan perampok tersebut. Selamatlah ia!
Perjalanan Ibn Baththuthah bersama para jamaah Tangier lainnya itu, menempuh keringnya hawa Laut Mediterranea dan di tengah teriknya daratan berpasir Afrika Utara, hanya dengan berjalan kaki. Selepas menempuh jarak sekitar 3.500 kilometer, Kota Alexandria menjadi kota pertama yang ia singgahi. Selepas itu, ia mampir di Kairo beberapa lama. Dari Kairo, ia kemudian melanjutkan perjalanannnya dengan melintasi rute yang melalui Kota Bait Al-Maqdis, Aleppo, dan Damaskus, bersama kafilah para jamaah haji yang menuju Makkah. Tetap dengan berjalan kaki. Rombongan itu berhasil mencapai Makkah dalam waktu 18 bulan, pada Dzulqa‘dah 726 H/Oktober 1326 M. Sebulan menjelang dimulainya ibadah haji tahun itu.
Ternyata, selepas itu, jarak yang kemudian Ibn Baththutah lintasi tak hanya sekitar 5.000 kilometer saja. Tapi, lebih dari 100.000 kilometer! Hal itu berbeda sekali dengan langkah sebagian besar kaum Muslim kala itu yang selepas naik haji lantas kembali ke negeri mereka, karena kondisi kala itu tak memungkinkan mereka berlama-lama berada di tengah-tengah perjalanan. Tentu saja, karena keamanan dan sarana transportasi belum terjamin dan selancar dewasa ini. Ketika Ibn Baththuthah memulai kelananya, hal itu terjadi lebih dari 125 tahun sebelum Christopher Columbus, Vasco da Gama, dan Ferdinand Magellan melakukan kelananya. Tak aneh jika Ibn Baththuthah kerap disebut sebagai “pengelana masa pertengahan” dan “pengelana seluruh kawasan dunia Islam” di masanya.
Memang, Ibn Baththuthah adalah seorang pengelana dan petualang sejati. Mengapa?
Karena lewat petualangan dan kelana tersebut, ia berkesempatan mengunjungi pelbagai kawasan dunia kala itu: Spanyol, Rusia, Turki, Persia, India, China, dan seluruh Semenanjung Arab. Tidak hanya itu. Catatannya tentang pelbagai kawasan yang ia kunjungi, baik apakah tentang aspek keagamaan, sosial, dan politik, mampu memberikan gambaran dan pencerahan tentang kebudayaan yang berkembang di kawasan yang ia kunjungi itu. Menurut para pakar, jarak yang dilintasi Ibn Baththuthah dalam perjalanannya itu tak tertandingi oleh siapa pun hingga ditemukannya kapal uap. Termasuk Marco Polo, Magellan, dan Columbus! Tokoh suku Limatah, Berber, dan putra seorang qâdhî ini memang suka berkelana dan berpetualang. Dua puluh delapan tahun dari usianya, antara 725-754 H/1325-1353 M, ia habiskan di tengah-tengah perjalanan.
Selepas mengunjungi Makkah untuk menunaikan ibadah haji, Ibn Baththuthah lantas menuju Madinah, Damaskus (selama di kota ini ia menikah dan memiliki seorang putra yang tak pernah bertemu dengannya), Irak, Iran, lalu kembali ke Makkah. Di Kota Suci itu, untuk kedua kalinya, ia bermukim selama tiga tahun. Selama itu, pengelana yang haus ilmu ini kemudian menimba ilmu kepada sejumlah ulama dan ilmuwan. Puas menimba ilmu, dari Tanah Suci ia lantas mengayunkan langkah-langkahnya ke Yaman, lantas menyeberangi Laut Merah menuju Afrika dan mengunjungi Ethiopia, Mogadishu, Mombassa, Zanzibar, dan Kilwa.
Dari Somalia Ibn Baththuthah kemudian menapakkan kaki menuju Suriah. Selepas melintasi Suriah, ia kemudian memasuki wilayah Anatolia (kala itu berada di bawah kekuasaan Dinasti Saljuq), Turki, naik sebuah kapal Genoa. Dari Alanya, ia kemudian menuju Konya lewat jalan darat. Selepas itu, ia menuju Sinope yang terletak di tepi Laut Hitam. Perjalanannya selanjutnya mengantarkannya ke Caffa (kini Theodisia), Ozbeg, dan Astrakhan. Dari Astrakhan, ia kemudian balik ke Constantinople (kini Istanbul dan kala itu masih di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi Timur). Betapa ia sangat mengagumi kota terakhir itu. Di kota itu, menurut catatannya, ia melihat banyak pendeta dan biarawati. Di kota itu pula, ia bertemu dengan Kaisar Andronicus III Palaelogus dan mengunjungi St. Hagia Sophia. Tapi, ia menolak masuk ke dalam gereja itu (kala itu belum lagi diubah menjadi masjid, karena masih di bawah kekuasaan Kekairan Romawi Timur). Alasannya, ia tak mau melintas di bawah palang salib.
Selepas sekitar satu bulan berada di Constantinople, Ibn Baththuthah kemudian balik lagi ke Astrakhan. Dari Astrakhan, dengan melintasi Laut Kaspia dan Aral, ia kemudian menuju Bukhara dan Samarkand. Dari Bukhara dan Samarkand, ia kemudian mengarahkan perjalanan ke selatan, menuju Afghanistan. Selepas itu, India menjadi kawasan berikutnya yang ia kunjungi. Kala itu, India berada di bawah kekuasaan Dinasti Tughluq dan di bawah pimpinan Ghiyatsuddin Muhammad Syah II (726-752 H/1325-1351 M). Selama di Benua India itu, ia menikah kembali dan memiliki seorang putri.
Selepas selama sekitar delapan tahun bermukim di India, antara lain menjabat sebagai seorang qâdhî, Ibn Baththuthah lantas menuju China, sebagai duta Kesultanan Delhi kepada penguasa China kala itu. Rombongan diplomatik ini berangkat pada akhir musim panas pada tahun 741 H/1341 M menuju pelabuhan Cambay. Namun, di tengah perjalanan, mereka diserang pemberontak Hindu yang menguasai daerah pedesaan India. Ibn Baththuthah tertangkap. Tapi, kemudian ia berhasil melarikan diri dan bergabung dengan rombongan yang tersisa. Mereka pun meneruskan perjalanan menuju China yang kala itu di bawah kekuasaan Dinasti Yuan. “Oh, ternyata tiada warga dunia mana pun yang lebih kaya ketimbang warga China,” tulisnya tentang negeri satu itu. Di China, ia antara lain berkunjung ke Hangchow dan Beijing. “Hangchow adalah kota terbesar di dunia yang pernah kulihat,” tulis lebih lanjut sang pengelana yang satu ini.
Usai dari China, Ibn Baththuthah lantas mampir di Indonesia selama 15 hari dan tak kembali ke India. Dari Indonesia ia lantas menuju ke kawasan Teluk Persia dan berhenti beberapa lama di Kepulauan Maldive. Nah, di kepulauan itu, ia menikah kembali dan memiliki seorang putra. Tuturnya tentang perkawinan di kepulauan itu kala itu, “Di kepulauan ini, mudah sekali bagi seorang untuk melangsungkan pernikahan. Ini karena ia tak perlu membayar mahal mahar…Tak aneh, ketika sebuah kapal berlabuh di pula itu, para awak kapal pun segera menikahi perempuan-perempuan kepulauan itu. Kemudian, ketika akan berangkat lagi, mereka pun menceraikan istri-istri mereka. Ini semacam nikah temporer. Kaum perempuan kepulauan itu tidak pernah meninggalkan negeri mereka.”
Selepas beberapa lama di Kepulauan Maldive, Ibn Baththuthah lantas meneruskan perjalanannya menuju Damaskus, Suriah. Di kota terakhir ini, ia bermaksud bertemu dengan seorang putranya yang ia tinggalkan 20 tahun sebelumnya. Ternyata, sang putra telah berpulang 15 tahun sebelum kedatangannya kembali ke kota itu. Selepas beberapa lama di Damaskus, ia kemudian meneruskan perjalanannya menuju Mesir. Tapi, segera ia meninggalkan Mesir, karena negeri itu kala itu sedang dihajar wabah kolera. Andalusia (kini Spanyol) menjadi tempat kunjungannya yang berikut, sesudah itu ia menuju kawasan Afrika Tengah. Terminal terakhir perjalanannya adalah Fez, Maroko. Ia tiba di kota tersebut pada 756 H/1357 M. Di kota itu pulalah, ia selepas sempat mengunjungi Andalusia, pada 770 H/1368-69 atau 779 H/1377 M, ia berpulang.
Kisah petualangan Ibn Baththuthah yang panjang dan sangat menarik itu kemudian, atas permintaan penguasa Maroko kala itu, Abu ‘Inan Faris, ia tuangkan dalam karya besarnya Tuhfah Al-Nazhâr fî Gharâ’ib Al-Amshâr wa ‘Ajâib Al-Asfâr yang juga dikenal dengan judul Rihlah Ibn Baththûthah, sebuah karya yang baru ditemukan 300 tahun kemudian di Aljazair. Karya yang satu ini berisi catatan mengenai negara-negara yang ia kunjungi. Kini, naskah asli karya ini tersimpan di Perpustakaan Nasional Perancis di Paris dan telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa asing, antara lain ke dalam bahasa Inggris (1245 H/1829 M), bahasa Jerman (1331 H/1912 M), dan berbagai bahasa Eropa lainnya.
Demikianlah kisah perjalanan panjang Ibn Baththuthah. Kisah perjalanan yang membuat dirinya tertoreh sebagai “pengelana sejati” dan memberikan banyak inspirasi bagi para pengelana dan petualang selepas ia.







.JPG)