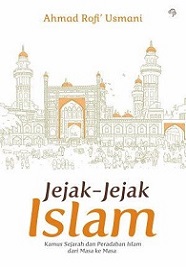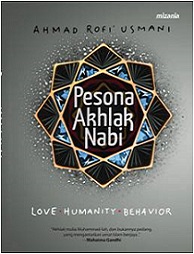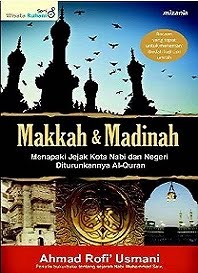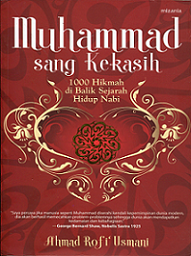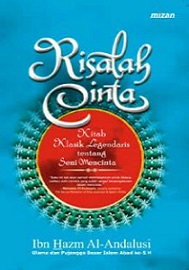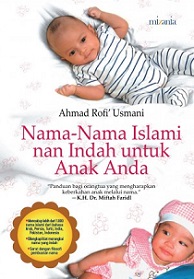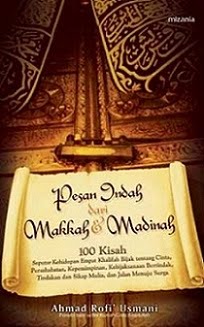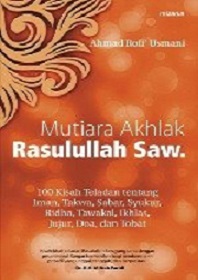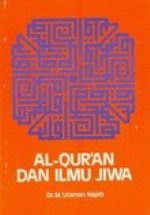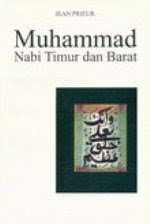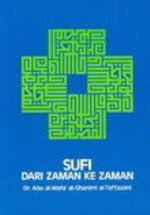RENUNGAN AWAL TAHUN HIJRIAH 1437:
Kenapa Kami Suka “Kluyuran”
“Mau jalan-jalan lagi ya? Sekeluarga ya?”
Demikian ucap kakak sulung saya kepada saya, sebelum saya
sekeluarga bertolak ke Jepang antara 6-12 Oktober yang lalu. “He, he, he. Iya,
Mbak. Kan saya sama Mona (putri sulung
kami) belum pernah ke sana. Kalau istri dan Naila (putri bungsu kami) kan sudah
pernah ke sana.”
“Ke mana saja?”
“Mona dan Naila yang merancang dan memimpin kami. Mereka
yang tahu, ke mana kami akan melangkah. Seperti dua tahun yang lalu ketika kami
ke Korea.”
“Selamat jalan, ya. Semoga mendapatkan ilmu dan
pengalaman yang bermanfaat.”
“Terima kasih, Mbak.”
“Kluyuran” alias jalan-jalan, memang, sudah menjadi
kegiatan kami sejak bertahun-tahun yang lalu. Saya sudah mulai “kluyuran” sejak
tahun 1978. Istri sejak sekitar tahun 1989. Sedangkan putri sulung kami sejak
tahun 2001, juga putri bungsu kami. Meski saya yang paling lama, tapi
“prestasi” saya kalah sama “prestasi” istri. Saya baru mengunjungi empat benua.
Istri sudah melalangbuana ke lima benua. Putri sulung dan bungsu kami bersaing:
yang sulung sudah menjejakkan kaki di 25 provinsi Indonesia, yang bungsu 16
provinsi. Yang sulung sudah menengok seluruh negara Asean, yang bungsu juga
sama minus Filipina, di samping Eropa, Hong Kong, China, Macau, dan Korea. Tentu
saja di luar kegiatan beribadah ke Tanah Suci.
Mengapa kami suka “kluyuran”?
Bagi kami, “kluyuran” memang mengasyikkan: selain menimba
ilmu, mendapatkan pengalaman baru, mengenal lebih dekat dengan berbagai bangsa
dengan kultur dan kebiasaan serta pencapaian mereka, kami bisa saling berbagi
ilmu dan pengalaman sambil jalan-jalan.
Dalam berbagi ilmu, kami memiliki “keunggulan” yang tidak sama. Saya
memiliki latar belakang pendidikan keagamaan, istri memiliki latar belakang
medis, putri sulung kami memiliki latar belakang teknik industri dan teknik
perminyakan, dan putri bungsu kami memiliki latar belakang teknik informatika
dan manajemen telekomunikasi. Sehingga, dapat dikatakan, saya ini masuk dalam
“kelompok minoritas”: mereka bertiga memiliki latar belakang pendidikan
eksakta, sedangkan saya beda sendiri, berlatar belakang pendidikan pesantren.
Dengan latar belakang pendidikan yang beragam tersebut, kami bisa melihat
setiap persoalan dengan sudut pandang yang kaya.
Di sisi lain, mulai dua tahun yang lalu, ketika kami “kluyuran”
ke Korea, dalam hal pendanaan, perancangan skedul perjalanan, pengurusan visa,
pengurusan bagasi dan “komandan” perjalanan kami serahkan sepenuhnya kepada dua
putri kami. Saya dan istri menempati posisi pengikut yang patuh pada arahan
mereka. Hal itu karena dua putri kami, dengan latar belakang pendidikan yang
membekali mereka dengan penguasan teknologi, lebih cepat mengantisipasi dan
menghadapi segala hal yang terjadi di perjalanan. Contoh, sistem transportasi
di Seoul dan Tokyo dengan mudah dapat mereka pecahkan dan hadapi. Karena itu,
dalam perjalanan bersama mereka, saya kini mendapat tugas sebagai “chef”, ya
tukang masak. Sayalah yang menyiapkan bekal makanan dan memasaknya setiap subuh
sebelum kami “kluyuran”. Tugas yang menyenangkan, tapi membuat tubuh saya kian
tambun.
Selain mendapatkan berbagai manfaat tersebut, entah
kenapa, kerap kali ide awal buku-buku yang saya tulis lahir di tengah
perjalanan. Misal, Ensiklopedia Tokoh Muslim, yang saya tulis, lahir
ketika saya sedang “kluyuran” di Istanbul. Malah, ide awal pendirian Pesantren
Mini kami muncul ketika kami sedang bersilaturahmi di rumah seorang sahabat di
Kajang, Kuala Lumpur. Malah, ide pendirian Diabetic Center di rumah sakit tempat
istri kerja (dua bulan yang lalu meraih predikat sebagai Diabetic Center
terbaik tingkat nasional), di bawah komandan istri, muncul ketika istri “kluyuran” di Bangkok.
Ide-ide itu kemudian kami kembangkan dan laksanakan dengan sebaik-baiknya.
Tentu, masih banyak manfaat lain yang kami dapatkan lewat
perjalanan. Apa pun halnya, perjalanan sekeluarga kini menjadi bagian dari
acara kami sekeluarga. Dan, perjalanan, dengan cara kami, tidak selalu berbiaya
tinggi dan lewat perjalanan, seperti diperintahkan Rasulullah Saw., kami
berusaha “memungut hikmah yang terserak di mana-mana.” Dan, akhirnya, “Selamat Tahun Baru 1437 H,
Semoga Allah Swt. Senantiasa Memberkahi dan Meridhai Kita Semua.” Salam.