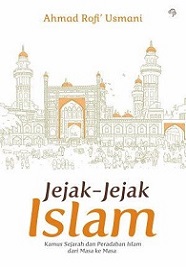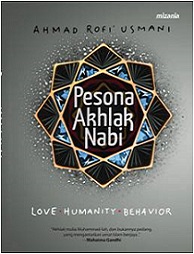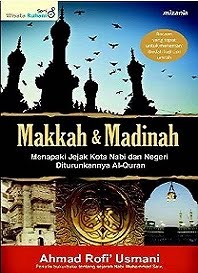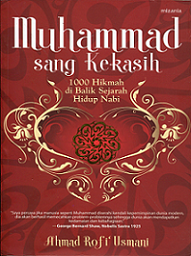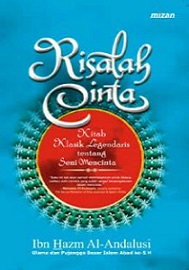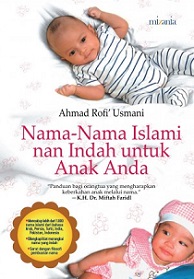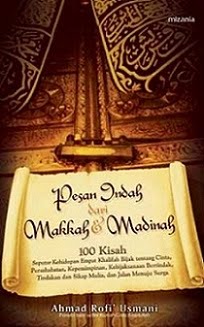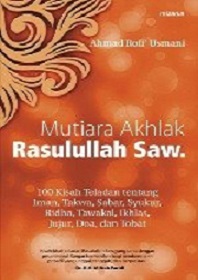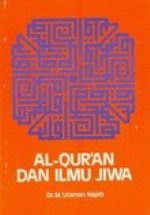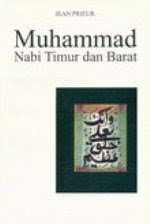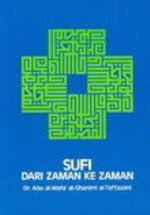Tadi pagi, 28 Desember 2009, tak lama setibanya kembali dari Semarang selama dua hari, untuk menghadiri acara pernikahan, saya pun membuka facebook. “Oh, menarik sekali foto ini,” gumam saya ketika melihat sebuah foto (lihat di samping) di sebuah alamat facebook yang menampilkan foto Gus Mus sedang mendampingi Gus Dur. Tanpa lama-lama mencermati foto itu, segera saya menyadari bahwa foto itu diambil di tempat kediaman Gus Mus di Desa Leteh, Rembang, Jawa Tengah. Mengapa demikian? Ini karena beberapa hari yang lalu Gus Mus mengabarkan (lewat facebook “Simbah Kakung”), bahwa saat itu Gus Dur sedang berkunjung ke pesantren Gus Mus, Raudhatut Tholibin. Yang menggembirakan, dalam kunjungan itu, Gus Dur berkenan menikmati hidangan yang disajikan. Padahal, selama beberapa lama sebelum itu Gus Dur sama sekali tidak berkenan menyantap apa pun.
Karena tubuh terasa lelah selepas semalam menempuh perjalanan dari Semarang, tak lama selepas membuka facebook itu saya tak kuasa menahan kantuk dan akhirnya saya pun tertidur pulas. Eh, ketika dalam tidur pula itu, saya bermimpi sedang berada di Kairo, Mesir. Anehnya, dalam mimpi itu saya masih muda usia dan tahun dalam mimpi itu menunjuk awal tahun 1981. Saat itu waktu menunjuk sekitar jam satu siang. Yang menarik, saat itu saya sedang keluar dari Masjid Al-Husain bin ‘Ali, tempat kepala putra ‘Ali bin Abu Thalib itu disemayamkan. Tak lama selepas menapakkan kaki dan menengok ke arah Khan Khalili, sebuah pasar tradisional kerajinan terkemuka di samping kanan masjid itu, tiba-tiba saya melihat melihat Gus Dur (yang tampak masih sehat dan bisa melihat) dan Gus Mus (yang belum banyak memiliki uban dan tampak ganteng) sedang duduk di sebuah kafe di samping pelataran masjid itu. Duh, betapa gembira hati saya melihat dua tokoh yang acap “membikin ulah” di pentas budaya Indonesia itu. Tanpa berpikir panjang, apalagi melihat mereka hanya berdua tanpa disertai “para punakawan”, saya pun segera berlari menuju ke arah mereka. Begitu dekat dengan mereka, terjadilah perbincangan sebagai berikut:
“Assalamu’alaikum Gus Dur dan Gus Mus…” ucap saya kepada Gus Dur dan Gus Mus yang sedang menikmati teh Mesir.
“Wa’alaikumussalam… “, jawab Gus Dur. “Anda kalau tak salah seorang mahasiswa Indonesia yang tinggal di Manial Raudah, ya ? Dua tahun yang lalu saya ketemu Anda. Bukankah Anda keponakan Maghfur?”
“Wa’alaikumussalam…” sahut Gus Mus. “Betul, Mas Dur. Dia keponakan Maghfur dari Cepu. Dia tinggal di sebuah flat dekat flat Mas Harun Zaini dan Mas Zabidi Ahmad, tempat kita menginap. Mas Dur, saya pernah ketemu dia, ketika saya menengok adik saya, Adib, di Pesantren Krapyak Yogyakarta. Dia pernah segotakan dengan adik saya. Ngapain Anda dari Masjid Al-Husain? Lagi cari inspirasi atau lagi menyepi ?”
Mendengar jawaban, komentar, dan pertanyaan para tokoh yang saya hormati itu saya sejenak kebingungan. Tak tahu harus menjawab apa. Tapi, tak lama kemudian, saya menjawab sekenanya, “Gus Dur dan Gus Mus…Benar saya tadi dari Masjid Al-Husain. Kalau dikatakan mencari inspirasi, mungkin juga benar. Saya sedang mencari inspirasi bagaimana agar tesis saya segera diterima oleh Majlis Al-A’la li Al-Jami’at. Terus terang, saya sudah gak tahu lagi, apa yang harus saya lakukan menghadapi birokrasi di negeri ini. Di satu sisi, saya merasa bersyukur dapat menimba ilmu di sini. Tapi, di sisi lain, birokrasi di negeri ini amat dan amat melelahkan. Dan, kalau dikatakan lagi menyepi, itu juga gak salah. Sebab, dengan bertafakkur di masjid itu, entah kenapa setiap kali keluar dari masjid itu saya mendapatkan energi baru : semangat Al-Husain bin ‘Ali yang tak mudah patah arang memberikan semangat bagi saya untuk tetap melanjutkan studi saya di sini…Mohon maaf, saya tidak bermaksud berkeluh kesah. ..Tentu Gus Dur dan Gus Mus lebih mafhum tentang birokrasi di negeri ini ketimbang saya.”
“Gitu saja repot !” sergah Gus Dur “Terus saja belajar dan pantang menyerah ! Dulu, ketika saya masih menimba di sini, bersama Mustofa ini, keadaannya jauh lebih payah dan parah. Anda tentu tahu, ketika saya sedang belajar di sini, negeri ini dalam keadaan perang. Bayangkan, saat itu untuk mendapatkan beras dan gula sulitnya bukan main. Semua serba antri dan barang-barang itu hanya ada di koperasi. Setiap malam, lampu-lampu harus diredupkan dan malah dipadamkan. Setiap kali sirene berbunyi, kami harus segera harus lari ke bunker-bunker di depan flat yang kami tinggali. Meski begitu, kami tidak pernah berhenti menimba ilmu. Gelar gak usah dijadikan patokan. Kalau gelar berhasil diraih, ya alhamdulillah. Kalau gelar gak teraih, ilmu sebanyak-banyaknya harus kita bawa pulang ke negeri kita. Apa gunanya dapat gelar doktor kalau ternyata kemampuannya memble. Bukan begitu “gaya” santri Kiai Ali Maksum dari Pondok Pesantren Krapyak (entah dari mana Gus Dur tahu bahwa saya pernah menimba ilmu di Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta) . Bayangkan, walau beliau hanya lulusan pesantren dan kemudian menimba di Makkah, tapi beliau kini menjadi seorang guru besar Tafsir Al-Qur’an yang disegani, walau beliau tanpa gelar sama sekali…Birokrasi di negeri ini jangan dijadikan alasan…Anda tahu maksud saya, kan?”
“Benar kata Mas Dur tadi…” sahut Gus Mus. “Kesulitan seyogianya tidak dijadikan alasan untuk tidak menimba ilmu sebaik-baiknya di negeri ini. Sebab, di sinilah sejatinya Anda bisa menimba ilmu-ilmu keislaman yang sangat kaya jika Anda tahu menyiasatinya. Khazanah ilmiah keislaman yang dimiliki negeri ini luar biasa kayanya… Baiklah, kayaknya Gus Dur saat ini sudah lapar. Ayo kita makan di math’am kawari ‘ (resto sup kaki kambing) di samping sebuah lorong di antara kedai-kedai di Khan Khalili itu. Dulu, math’am itu adalah langganan kami ketika kami lagi punya duit…Selepas itu, kita pergi ke Azbakiah, mencari buku-buku bekas yang gak ada di toko-toko buku…”
Kami pun kemudian menikmati makan siang di math‘am kawari ‘ itu.
Betapa saya bersyukur sekali siang itu, selain bisa bertemu dengan kedua tokoh itu tanpa direcoki oleh siapa pun, saya masih diajak menikmati kawari ‘ nan sangat lezat itu. Selepas menikmati kawari ‘, kami kemudian menikmati puding semolina, mahalabiyyah. Dan, tak lama selepas menikati sajian-sajian itu, Gus Mus tiba-tiba berucap kepada saya, “Kalau Anda gak keberatan, bisakah Anda hari ini mengantar kami jalan-jalan ke Azbakiah, kemudian menuju Musium Islam, Masjid Sayyidah Zainab, Makam Imam Syafi’i, Masjid Muhammad ‘Ali, toko-toko buku di seputar ‘Atabah, dan malam nanti kita langsung menuju markas Persatuan Pelajar Indonesia di Bab el-Louk. Bagaimana?”
“Sami‘na wa atha‘na, Gus Mus…” jawab saya, takzim.
Benar saja, tak lama selepas menikmati santap siang, kami dengan naik bus yang padat penumpang kemudian menuju Azbakiah. Naik bus yang demikian, Gus Dur dan Gus Mus senyum-senyum saja. Ketika telah berada di Azbakiah, di lokasi yang merupakan pusat buku-buku bekas itu Gus Dur dan Gus Mus menemukan sejumlah buku yang sangat berharga. Menurut mereka, kala mereka masih menjadi mahasiswa di Kairo mereka berdua sering berjam-jam memburu buku-buku berharga yang sudah tidak diterbitkan lagi dan selepas itu menonton film di sebuah gedung bioskop di Tal’at Harb St . Dan, dari Azbakiah, kami kemudian menuju ke arah Sayyidah Zainab dengan naik trem yang juga penuh dengan penumpang. Kami turun di halte dekat Musium Islam (yang kala itu masih menyatu dengan Dar Al-Kutub Al-Mishriyyah).
Kemudian, selepas menikmati pelbagai khazanah Islam di Musium Islam, kami menuju Dar Al-Kutub Al-Mishriyyah. Ketika berada di Perpustakaan Nasional Mesir itu, Gus Dur berpesan kepada saya, “Usahakan setiap minggu Anda kunjungi tempat-tempat historis di negeri ini. Mengapa demikian? Sedotlah semangat dan daya juang para tokoh terkemuka negeri ini. Saya misalnya, dulu, ketika berada di perpustakaan ini, selalu mencari di mana kursi yang biasa ditempati Thaha Husain, Mahmud Al-‘Aqqad, Ahmad Lutfi Al-Sayyid, atau Muhammad Husain Haikal. Dengan duduk di kursi-kursi itu, Anda akan bisa merasakan semangat belajar mereka dan mengapa mereka memilih lokasi itu. Cobalah, nanti Anda akan menemukan sendiri “sesuatu” yang luar biasa…”
“Baik, Gus Dur…” jawab saya, takzim.
Ketika Gus Dur sedang asyik melihat khazanah buku-buku yang ada di Dar Al-Kutub Al-Mishriyyah, tiba-tiba Gus Mus mendekati dan membisiki saya, “Tolong, camkan benar apa yang dikatakan Mas Dur tadi. Mas Dur bermaksud baik terhadap Anda. Pengalaman hidup Mas Dur kaya warna. Ambillah “mutiara-mutiara” kemilau yang ada pada dirinya, tapi dengan sikap kritis yang bijak. Saya sering tidak seiring pendapat dengannya. Tapi, saya tetap menghormatinya. Saya pun kadang-kadang berseberangan pandangan dengannya. Tapi, pandangan itu selalu saya sampaikan kepadanya dengan cara yang tidak membuat “gaya Jawa Timurannya” membara.”
“Gus Mus, kalau boleh tahu, bagaimana “gaya Jawa Timuran” Gus Dur?”
“Niatnya baik, tapi diungkapkan dengan seenaknya sendiri…” jawab Gus Mus seraya tersenyum.
Dari Musium Islam, kami kemudian menuju Masjid Sayyidah Zainab. Selepas itu, kami kemudian menuju ke Mesir Lama, untuk berziarah ke Makam Imam Syafi’i dan Imam Waki’. Lantas, menjelang magrib, kami telah tiba di Masjid Muhammad ‘Ali yang dilingkungi Benteng Shalahuddin Al-Ayyubi. Dan, ketika menjelang isya, kami telah tiba di sebuah flat di Bab el-Louk, sebuah flat yang menjadi markas besar Persatuan Pelajar Indonesia di Mesir yang terletak tidak jauh dari Midan Tahrir dan American University in Cairo. Di flat itu, tentu saja kedatangan Gus Dur dan Gus Mus disambut hangat oleh para mahasiswa Indonesia yang sedang menimba ilmu di Mesir.
Eh, keriuhan para mahasiswa Indonesia yang menyambut kedatangan Gus Dur dan Gus Mus itu ternyata membuat saya terjaga dari tidur yang sangat pulas. Dan, ternyata, semua kejadian yang saya alami tadi hanya mimpi belaka.










.jpg)