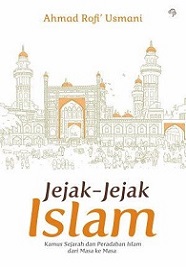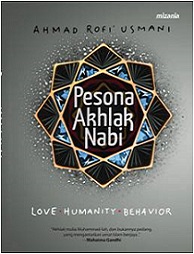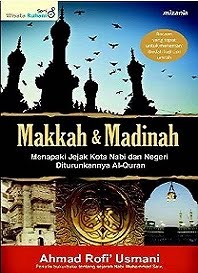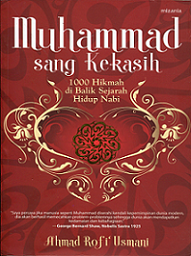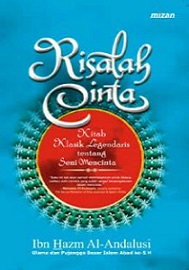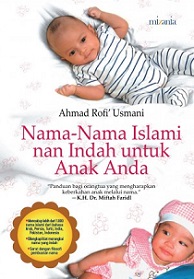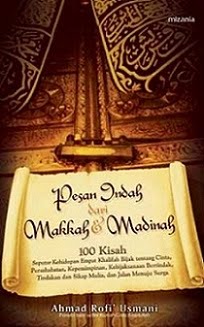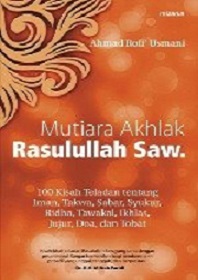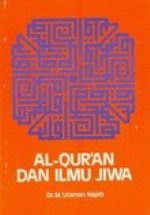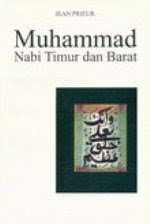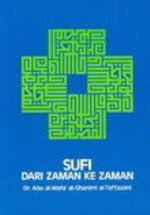IBUKU
“Masya Allah, tak terasa 37 tahun lewat ketika pertama
kali aku menjejakkan kaki di Negeri Piramid.”
Demikian gumam bibir saya, tadi pagi, ketika teringat
perjalanan hidup diri. Ya, tepat pada tanggal sama dengan tanggal hari ini, 11
Desember, itulah hari pertama kali kedua kaki saya menjejakkan kaki di ibukota
Mesir: Kairo 37 tahun yang silam. Seperti
pernah saya tulis dalam sebuah karya berjudul Dari Istanbul hingga Eksotisme
Masjid Al-Azhar, pada tanggal itu, tepatnya pada Senin, 10 Muharram
1399 H/11 Desember 1978 M, itulah hari pertama kali saya menjejakkan kaki di
Kota Kairo selepas naik pesawat terbang Royal Air Maroc selama sekitar dua jam dari
Kota Jeddah. Tanpa mengenal
siapa pun. Juga, belum mengenal sama sekali tentang ibukota Mesir itu. Yang
saya ketahui, Mesir adalah sebuah “ladang perburuan” ilmu. Itu saja dan tak
lebih. Saya pun tak tahu, setiba di Kairo mau menemui siapa, tinggal di mana,
dan meneruskan studi di mana.
Malah, menjelang
tiba di Kota Kairo, ternyata pesawat terbang yang saya naiki saat itu mengalami kejadian yang tak pernah
saya lupakan hingga kini pesawat
itu terjerembab dalam ruang hampa udara dan terhempas keras sekali. Cuaca
mendekati Kota Kairo kala itu benar-benar tak bersahabat. Musim dingin di bulan
Desember dengan badai sedang menghantui. Hampir setengah jam lamanya pesawat
terbang tersebut bermain akrobat. Demikianlah
“sambutan meriah” yang diberikan kepada saya menjelang kedatangan saya pertama
kali ke Kota Seribu Menara itu.
Kejadian demi
kejadian yang saya alami itu kian menanamkan keyakinan dalam diri saya, manusia
hanya kuasa berikhtiar dan Allah Swt. kuasa atas segala sesuatu. Di
samping itu, dalam hidup kadang diperlukan kenekadan dan keberanian mengambil
keputusan yang berisiko tinggi. Yang tak kalah penting, menurut saya, adalah
doa orang tua. Khususnya doa seorang ibu.
Mungkin, karena doa dan keinginan Ibuku yang sangat kuat agar saya menimba ilmu
kembali, tak lebih dari sebulan setiba di Kairo, saya telah diterima sebagai
mahasiswa di dua universitas sekaligus: Universitas Al-Azhar dan Universitas
Kairo. Ya, dua universitas sekaligus. Ini karena saya mengajukan dua ijazah:
untuk Universitas Al-Azhar saya mengajukan ijazah sarjana muda dan untuk
Universitas Kairo saya mengajukan ijazah sarjana penuh. Ternyata, pengajuan
saya diterima oleh kedua universitas itu. Padahal, banyak teman-teman yang
telah lama mendaftarkan diri di Universitas Al-Azhar tak kunjung beres
urusannya.
Ibuku, bagi saya, memang luar biasa.
Ketika masih berusia tidak lebih empat tahun, Ibuku telah
ditinggalkan ibunya, seorang Ibu Nyai, alias istri seorang kiai. Ibuku memang
memiliki “darah” kiai: ibunya seorang Ibu Nyai, ayahnya seorang kiai terkemuka
di tempat kelahirannya, Cepu, kakeknya seorang kiai terkemuka di Karesidenan
Bojonegoro, Jawa Timur, dan suaminya juga seorang kiai di Blora. Ibuku, seperti
halnya kebanyakan ibu-ibu seusia dengannya, tidak pernah menempuh pendidikan
umum. Ia hanya menerima pendidikan dalam lingkungan keluarga dan mengaji di lingkungan pesantren di bawah
pimpinan ayahnya: seorang kiai yang hafal Al-Quran dan menimba ilmu di sederet
pesantren. Termasuk di Pesantren Syaikhona Kholil Bangkalan, beberapa tahun
menimba ilmu di Makkah, dan Pesantren Krapyak Yogyakarta: untuk mendalami qira’ah
sab’ah kepada K.H. Munawwir.
Meski tidak pernah mengikuti pendidikan formal, Ibuku
seorang “pemburu” ilmu yang luar biasa. Setelah bisa membaca dan menulis
tulisan Arab dan Latin, dapat dikatakan tiada hari baginya tanpa membaca
Al-Quran dan buku. Tak aneh jika ketika telah berusia sekitar 40 tahun, selain
mengajar Al-Quran, Ibuku juga mengajar di Sekolah Penjenang Kesehatan. Padahal,
Ibuku tidak pernah menempuh pendidikan formal apa pun. Di sisi lain, Ibuku
seorang penyabar, tidak pernah mengeluh, dan sangat menaruh perhatian terhadap
pendidikan putra dan putrinya. Yang menarik, meski hidup sehari-hari di
lingkungan pesantren, putra dan putrinya diarahkan untuk menimba di luar
pesantren hingga mereka berhasil memasuki perguruan-perguruan tinggi umum: ITB,
UI, dan UNPAD. Lain halnya dengan saya. Entah kenapa, saya sejak kecil
diarahkan ke pesantren. Mungkin, saya anak yang malas sekolah: umur 7 tahun
baru mau masuk sekolah dasar. Sedangkan saudara-saudara saya umur 5 tahun rata-rata sudah masuk sekolah dasar.
Sejatinya, saya sejak awal menolak keinginan Ibuku untuk
menimba ilmu di Timur Tengah. Tetapi, dengan sabar, dan setelah berhasil
mengantarkan dua adik lelakinya mengambil program s-3 di Universitas Ummu
Al-Qura, Makkah, dan Universitas Harvard, Amerika Serikat, Ibuku akhirnya
berhasil memotivasi saya untuk berangkat ke sana. Ucap Ibuku, “Rofi’, jangan
engkau tolak dambaan Ibu. Carilah
ilmu dan pengalaman yang bermanfaat di
mana pun, sampai pun ke negeri orang. Itulah yang terpenting. Masalah
gelar, itu tidak Ibu haruskan untuk diraih. Engkau tentu tahu, Ibu bukan orang
yang pernah meniti pendidikan formal, namun Ibu tak pernah berhenti menimba
ilmu dan pengalaman yang bermanfaat. Berangkatlah dan ikuti jejak langkah dua
pamanmu itu.”
“Memburu ilmu dan pengalaman”, sesuai pesan Ibuku, akhirnya
yang saya buru, bukan gelar. Hal itulah yang saya
lakukan hingga kini: dengan kluyuran ke mana-mana. Dan, pada hari ini, secara
khusus saya berdoa panjang untuk Ibuku. Kiranya beliau berbahagia di sisi
Tuhannya, amin.