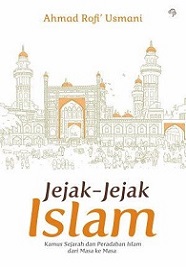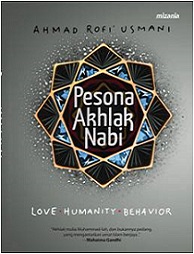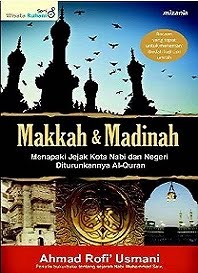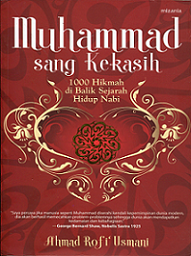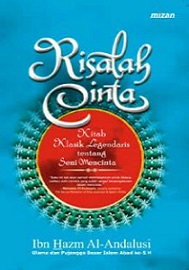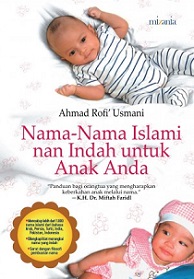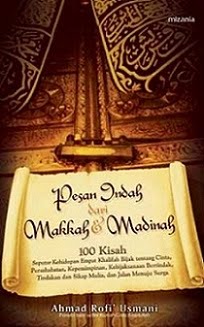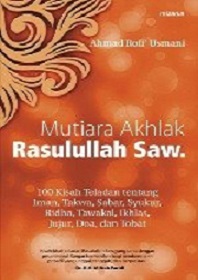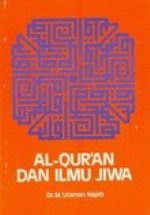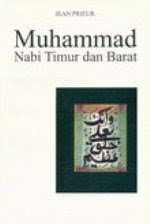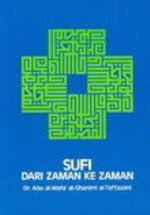ITAEWON: SEBUAH DISTRIK MENARIK DI KOTA SEOUL:
Perjalanan Santri Ndeso dan Keluarga ke Negeri Ginseng
(2)
“Let’s go Itaewon, Pakde, Bude, Bapak, Ibu, dan adik!”
Demikian perintah tour leader kami (alias Mona) selepas kami
berenam beristirahat di “Operation Room One” (alias tempat kami menginap di Seodaemun)
pada Selasa, 5 November 2013 yang lalu. Mengapa Itaewon yang dijadikan sebagai
sasaran pertama ‘kluyuran’ kami?
“Hari ini kan Tahun Baru Hijriah 1435 H. Karena di
Itaewon terdapat Masjid Sentral Seoul, maka distrik itu merupakan tempat paling
tepat menjadi tempat pertama yang kita kunjungi di Kota Seoul hari ini,” urai
Mona.
“Naik apa kita ke sana? Pakai metro atau bus?” tanya
saya.
“Kita manfaatkan saja bus gratis yang disediakan tempat
menginap ini. Menghemat dana dan nyaman, hehehe,” jawab tour leader tidak resmi
itu. “Di Itaewon, selain mengunjungi Masjid Sentral Seoul, kita akan makan
siang di sana. Kali ini, kita makan di luar. Tampaknya, di antara kita ada yang
kelaparan, karena naik pesawat terbang yang tidak menyajikan makanan kecuali
dengan membeli, hehehe.”
“Saya sudah makan, lo. Beli di pesawat terbang,” sahut
Pakde Min (kakak istri) sambil senyum-senyum. Tapi, Pakde tampaknya masih
lapar, karena mungkin belum menikmati makan pagi di pesawat terbang.
“Selanjutnya, setelah itu, selama dalam perjalanan ini,
kita akan menikmati masakan yang dibikin Bude Us dan Ibu,” urai Mona lebih
lanjut. “Selain lebih hemat, juga kehalalannya lebih terjamin. Kemudian, setelah
dari Itaewon, kita lihat nanti: apakah kita naik bus atau metro. Atau jika
kuat, kita jalan kaki saja. Dari Itaewon, kita akan menuju tempat penginapan di Sejong-daero. Nanti sore, kita akan ke Gwanghamun Square. Oke?”
“Siap, komandan, ” sahut saya dalam hati, begitu
mendengar uraian Mona tersebut, sambil menatap keluar jendela dan melihat
lingkungan di seputar tempat menginap kami di Seodaemun.
Menaati perintah sang komandan perjalanan, segera kami
berlima pun berkemas dan bersiap-siap untuk ‘menikmati’ Kota Seoul dengan
metromini yang disediakan tempat menginap kami di Seodaemun. Kami berenam,
setelah sampai di Kota Seoul, memang masih menyatu dan belum memisahkan diri di
tempat penginapan masing-masing. Saya sendiri segera menyiapkan jaket, payung,
dan air minum yang saya campur tablet vitamin C dosis tinggi (untuk menjaga
ketahanan tubuh dalam menghadapi musim dingin) ke dalam “tas tempur” saya, alias
tas punggung saya. Kemudian, ketika metromini yang akan kami naiki telah siap,
kami pun segera naik metromini dengan rute: Hongje Subway Station-Limkwang Tower
East-Seoul Subway Station-Itaewon-Ace Tower-YTN Tower-Namdaemun-Hongje Subway
Station. Kali ini, tujuan kami adalah
Halte Itaewon.
Sepanjang perjalanan, menuju Itaewon, pandangan saya
terarah ke pelbagai sudut Kota Seoul. “Enak juga jadi anak buah,” gumam saya
dalam hati. “Tinggal ikut ke mana tour leader melangkah dan bebas menikmati
perjalanan.” Ya, menjadi anak buah, dalam perjalanan, memang enak. Ke mana tour
leader pergi, kita tinggal mengekor di belakangnya. Berbeda dengan
perjalanan-perjalanan sebelumnya, yang menempatkan saya dalam posisi sebagai tour
leader, kali ini kedudukan sebagai anak buah benar-benar saya nikmati. Karena
itu, kali ini saya lebih banyak menempatkan diri sebagai fotografer dadakan.
Apalagi setelah melihat tour leader, Mona, dan wakilnya, Naila, selalu siap dengan
smartphone dan note mereka: untuk mengecek sampai di lokasi mana metromini yang
kami naiki berada.
Kota Seoul saat itu, di musim gugur, tampak begitu indah. Daun-daun yang sedang
menguning dan memerah membuat kota itu
kian menawan. Sementara di sepanjang jalan, daun-daun tampak bertebaran dan
berserakan di mana-mana, di antara cuatan gedung-gedung dengan aneka ragam gaya
dan model. Tradisional maupun modern. Melihat pemandangan demikian, entah
kenapa tiba-tiba dalam benak saya mencuat kenangan ketika masih muda dan sedang
menimba ilmu di Kairo, Mesir pada awal 1980-an. Kenangan ketika malam, selepas
belajar bahasa Perancis di Mounira sampai sekitar pukul sembilan malam, harus
berjalan setengah berlari, untuk menghindari terpaan angin musim dingin sambil
menikmati dan menghitung satu demi satu bangunan-bangunan di jalan-jalan yang dilintasi.
Setelah menyusuri pelbagai sudut Kota Seoul selama
sekitar 40 menit, metromini yang kami naiki pun berhenti di sebuah halte yang
berada di depan sebuah Restoran McDonald. Suasana di Itaewon-ro itu, memang,
agak berbeda dengan suasana di pelbagai penjuru lainnya Kota Seoul. Suasana ‘internasional’
lebih mewarnai distrik itu. Khususnya ‘nuansa’ Timur Tengah dan Asia Selatan. Toko-toko di distrik ini, memang, lebih ‘warna-warni’
ketimbang di bagian-bagian lain Kota Seoul. Distrik ini sendiri, semula, merupakan desa kecil yang menjadi
tempat tinggal para pegawai pemerintahan dari Dinasti Joseon. Kemudian, selepas Perang Dunia II,
distrik itu menjadi “pangkalan” tentara Amerika Serikat. Dan, kini, distrik itu
tetap mempertahankan ‘suasananya’ yang ‘warna-warni’. Tidak aneh, karena itu,
jika di distrik ini pula banyak terdapat kaum Muslim lengkap dengan warung,
resto, maupun toko yang mereka miliki. Juga, sebuah masjid besar yang kemudian
disebut Masjid Sentral Seoul.
Meski tour leader dan wakilnya sudah membawa smartphone
dan note, ternyata kami agak kesulitan mencari lokasi Masjid Sentral Seoul yang
berlamat di 732-21 Hannam-dong, Yongsan-du, Seoul. Kemudian, ketika kami
kebingungan dalam mencari alamat masjid tersebut, tiba-tiba muncul dua cewek cantik
asal Libya. Lantas, ketika mereka berdua saya tanya, dengan bahasa Arab tentu
saja, tentang alamat masjid tersebut, eh mereka malah begitu bersemangat
mengantarkan kami menuju ke alamat tersebut. Melihat hal itu, Mona pun berucap,
“Hebat juga Bapak. Dua cewek cantik kok mau-maunya ngantar kita hanya karena
diajak ngomong bahasa Arab oleh Bapak, hehehe.”
“Lo, itulah kelebihan Bapak, hehehe,” canda saya. “Asal Ibu gak cemburu saja.”
Kedua cewek cantik asal Libya itu mengantarkan kami
hingga belokan menuju Usadan-ro. Sebelum berpisah, mereka saya minta untuk
berfoto bersama kami. Eh, lagi-lagi kedua cewek itu dengan penuh semangat
memenuhi permintaan kami. Selepas itu, kami pun berjalan pelan di sepanjang
jalan itu. Oh, di jalan itu ternyata banyak saudara-saudara kita dari Malaysia
yang sedang berbelanja di toko-toko yang bertebaran di sepanjang jalan itu.
Memang, di distrik ini ada sebuah guest house Malaysia (lihat: http://malaysianguesthouseinseoul.blogspot.com/)
dengan harga yang relatif terjangkau. Apalagi, di sekitar guest house itu
dengan mudah terdapat pelbagai sajian dan masakan halal. Guest house itu selalu penuh. Karena itu,
untuk mendapatkan kamar di situ, kita perlu memesannya jauh hari.
Setelah menyusuri Usudan-ro 10 gil, yang menanjak seperti
jalan-jalan kecil di Dago, Bandung, akhirnya sampailah kami di Masjid Sentral
Seoul yang tegak di atas lahan seluas sekitar 5,000 meter persegi. Alhamdulillah,
suatu kebahagiaan luar biasa terasakan dalam hati saya, karena dapat menikmati
Tahun Baru Hijriah 1435 H di sebuah masjid nun jauh di sebuah negara
non-Muslim. Kami pun shalat Zhuhur dan ‘Ashar
di masjid yang dilengkapi dengan sebuah madrasah untuk anak-anak: “Prince
Sultan Islamic School”. Kalau tidak keliru, salah seorang ustadz di madrasah
itu berasal dari Indonesia. Sayang, kami tidak bertemu dengannya.
Selepas dari berkunjung ke masjid yang terdiri dari tiga
lantai itu, lapar karena dingin mulai menyapa perut kami. Kami pun segera
menuju Murree Resto: Korea Muslim Food yang terletak di sebelah kiri masjid
yang mulai diresmikan pada 21 Mei 1976 M itu, di Usadan-ro 10 gil. Resto itu
milik seorang India Muslim yang beristrikan seorang Muslimah Korea. Resto ini
cukup terkenal. Wow, lezat sekali msakan korea yang mereka sajikan. Utamanya kimbibab,
buldogi, dan kimchi. Rasanya, bila kembali lagi ke Seoul, saya akan kembali ke
resto itu, insya Allah.
Setelah lelah menikmati Distrik Itaewon, kami kemudian
melanjutkan perjalanan menuju ke “Operation Room Two”, alias tempat penginapan
kedua yang diinapi Mona, Pakde, dan Bude, dengan naik subway alias metro.
Setelah beristirahat di sana, program kami sore hari itu menuju ke Gwanghamun
Square dan menikmati King Sejong Museum. (Bersambung: “ANDAI DI BAWAH MONAS ADA
MUSEUM SEPERTI INI: Perjalanan Santri Ndeso ke Negeri Ginseng (3)).