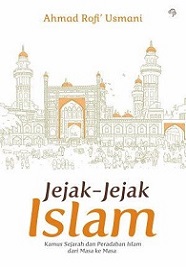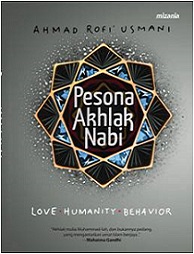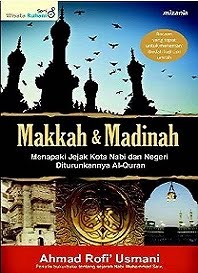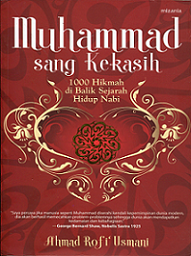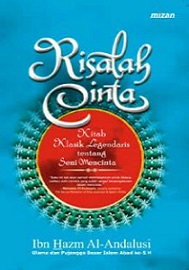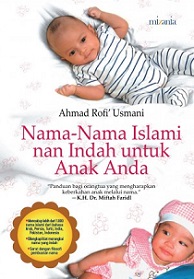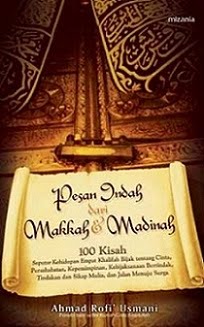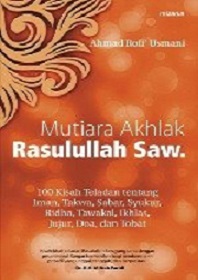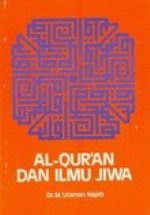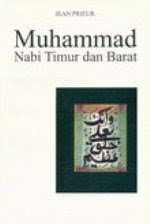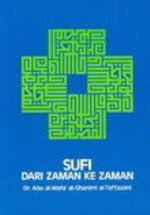KEDUDUKAN TINGGI INI MERUPAKAN MUSIBAH
Tadi malam,
ketika sedang menonton tivi dan melihat
pelantikan sejumlah menteri baru, entah kenapa benak saya tiba-tiba “terlempar”
ke Baghdad. Ya, ke sebuah kota yang
didirikan oleh seorang penguasa terkemuka Dinasti Abbasiyah, Abu Ja‘far
Al-Manshur, dan kini menjadi ibukota Irak. Entah kenapa pula, yang “melayang-melayang”
dalam benak saya tadi malam adalah kisah kegundahan seorang penguasa terkemuka
lain dinasti tersebut, seorang penguasa yang kerap ditampilkan dalam kisah Alf
Lailah wa Lailah (1001 Malam): Harun Al-Rasyid.
Kala itu, sang
penguasa tersebut sedang menunaikan ibadah haji di Makkah. Entah kenapa, pada
suatu malam, ketika berada di Kota Suci itu ia merasa sangat gelisah dan resah.
Karena tidak kuat menahan kegelisahannya yang kian mendera, meski saat itu di
tengah malam, sang penguasa kemudian memanggil Abu Al-Fadhl Al-Rabi‘ bin
Yunus, seorang menteri utama Dinasti ‘Abbasiyyah kala itu.
Ketika menteri
utama itu telah berada di hadapannya, Harun Al-Rasyid lantas berucap pelan
sambil menahan kegelisahannya, “Al-Rabi‘! Malam ini, bawalah aku kepada
seseorang yang kuasa menunjukkan kepadaku, siapakah sejatinya aku ini.”
“Ada keperluan apa, Amir
Al-Mukminin?” tanya sang menteri utama.
“Entah mengapa, saat ini aku merasa jemu
sekali dengan segala
kebesaran dan kebanggaan yang telah kurengkuh dan kunikmati selama ini!”
Mendengar ucapan sang penguasa, Abu
Al-Fadhl Al-Rabi‘ bin Yunus lantas membawa Harun Al-Rasyid ke rumah Sufyan bin
‘Uyainah. Tokoh terakhir itu
adalah seorang ahli hadis dan tafsir Al-Quran di Kota Suci kala itu. Nama
lengkapnya adalah Abu Muhammad Sufyan bin ‘Uyainah bin Maimun Al-Hilali
Al-Kufi.
Mendengar
seseorang mengetuk pintu, Sufyan bin ‘Uyainah menyahut, “Siapakah di luar?”
“Amir
Al-Mukminin!” jawab Abu Al-Fadhl Al-Rabi‘ bin Yunus.
“Mengapakah
Amir Al-Mukminin sudi menyusahkan diri? Mengapa tidak dikabarkan saja kepada
saya. Sehingga, saya datang sendiri untuk
menghadap?”
Mendengar
ucapan tersebut, Harun Al-Rasyid pun berucap kepada sang menteri utama, “Al-Rabi‘! Dia bukan orang yang kucari. Dia pun menjilat seperti
yang lain-lainnya.”
Ucapan itu, ternyata, didengar sang
ulama Makkah itu. Karena itu, dia pun berucap kepada sang penguasa, “Bila
demikian, wahai Amir Al-Mukminin, Al-Fudhail
bin ‘Iyadh adalah orang yang engkau cari. Pergilah kepadanya.”
Usai berucap
demikian, Sufyan bin ‘Uyainah kemudian membaca ayat Al-Quran, “Apakah
orang-orang yang berbuat aniaya menyangka bahwa kami akan mempersamakan mereka
dengan orang-orang yang beriman serta melakukan perbuatan-perbuatan salih?”
Harun
Al-Rasyid pun menimpali, “Andai aku menginginkan nasihat yang baik, tentu ayat
itu mencukupi bagiku.”
Mereka lantas
menuju ke rumah Al-Fudhail bin ‘Iyadh, seorang ulama Makkah yang terkenal hidup sangat sederhana.
Ketika mereka tiba di rumah Al-Fudhail, mereka lantas mengetuk pintu. Mendengar
ketukan di pintu rumahnya, Al-Fudhail bertanya dari dalam, “Siapakah di luar?”
“Amir Al-Mukminin!”
jawab Abu Al-Fadhl Al-Rabi‘ bin Yunus.
“Apa urusan dia dengan aku dan urusanku
dengan dia?” teriak Al-Fudhail.
“Al-Fudhail!
Bukankah merupakan kewajiban rakyat untuk mematuhi para pemegang kekuasaan?”
sergah Abu Al-Fadhl Al-Rabi‘ bin Yunus.
“Janganlah
kalian mengganggu aku!”
“Haruskah aku
mendobrak pintu dengan kekuasaanku sendiri atau dengan perintah Amir
Al-Mukminin?” sahut Abu Al-Fadhl Al-Rabi‘ bin Yunus.
“Tiada sesuatu
pun yang disebut kekuasaan!” ucap Al-Fudhail. “Jika engkau dengan paksa mendobrak
masuk, engkau tentu tahu
apa yang harus engkau lakukan!”
Harun
Al-Rasyid kemudian masuk ke dalam rumah Al-Fudhail bin ‘Iyadh. Begitu melihat
sang penguasa, Al-Fudhail lantas meniup lentera di depannya hingga padam agar
dia tidak dapat melihat wajah sang penguasa. Harun Al-Rasyid kemudian
mengulurkan tangannya dan disambut tangan Al-Fudhail yang kemudian berucap,
“Betapa lembut dan halus tangan ini! Kiranya tangan ini terhindar dari api
neraka!”
“Tuan Guru!
Berilah aku nasihat,” ucap Harun Al-Rasyid.
“Leluhurmu,
pamanda Rasulullah Saw. (maksudnya Al-‘Abbas bin ‘Abdul Muththalib), pernah
meminta kepada beliau agar dia dijadikan pemimpin bagi sebagian umat manusia.
Apa jawaban beliau? Jawab beliau, ‘Paman, bukankah aku pernah mengangkat engkau
untuk sesaat sebagai pemimpin dirimu sendiri?’ Dengan jawaban itu Rasulullah Saw. memaksudkan bahwa
sesaat mematuhi Allah adalah lebih baik daripada seribu tahun dipatuhi umat
manusia. Kemudian Rasulullah
Saw. menambahkan, ‘Kepemimpinan akan
menjadi sumber penyesalan di Hari Kebangkitan
kelak.’”
“Tuan Guru,
lanjutkanlah nasihatmu itu,” pinta Harun Al-Rasyid.
“Ketika
diangkat sebagai penguasa, ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz lantas memanggil Abu ‘Umar
Salim bin ‘Abdullah bin ‘Umar bin Al-Khaththab, Abu Al-Miqdam Raja’ bin Haiwah
bin Jarwal Al-Kindi, dan Abu Hamzah Muhammad bin Ka‘b bin Salim
bin Asad Al-Qurazhi. Ucap ‘Umar kepada mereka, ‘Hatiku sangat gundah dengan
musibah ini. Apakah yang harus kulakukan? Aku tahu, kedudukan tinggi ini
merupakan musibah, walau orang-orang lain memandang kedudukan sebagai karunia.’
Sahut Abu Al-Miqdam Raja’ bin Haiwah, “Amir Al-Mukminin! Jika engkau
ingin terlepas dari hukuman Allah di akhirat kelak, pandanglah setiap Muslim
yang lanjut usia laksana ayahandamu sendiri, setiap Muslim yang muda usia
laksana saudaramu sendiri, setiap Muslim yang masih kanak-kanak laksana putramu
sendiri. Dan, perlakukanlah mereka sebagaimana seharusnya seseorang
memperlakukan ayahanda, saudara, dan putranya.’”
“Tuan Guru,
lanjutkanlah nasihatmu itu,” pinta lagi Harun Al-Rasyid.
“Abu Al-Miqdam
Raja’ bin Haiwah lebih lanjut berucap, ‘Wahai Amir Al-Mukminin!
Anggaplah negeri yang engkau pimpin laksana rumahmu sendiri dan penduduknya
laksana keluargamu sendiri. Jenguklah ayahandamu, hormatilah saudaramu, dan
bersikap baiklah kepada putramu. Kusayangkan jika wajahmu yang tampan ini akan
terbakar hangus di neraka. Takutlah kepada Allah dan taatilah
perintah-perintah-Nya. Berhati-hatilah dan bersikaplah bijak, karena di hari
kebangkitan kelak Allah akan meminta pertanggungjawabanmu seputar setiap Muslim
yang engkau pimpin dan Dia akan memeriksa apakah engkau telah berlaku adil
kepada setiap orang. Ingatlah, manakala ada seorang perempuan uzur yang
tertidur dalam keadaan lapar, di hari kebangkitan kelak dia akan menarik pakaianmu
dan memberikan kesaksian yang akan memberatkan dirimu!’”
“Tuan Guru,
lanjutkanlah nasihatmu itu!”
“Abu Hamzah
Muhammad bin Ka‘b kemudian tampil memberikan nasihat, “Amir Al-Mukminin! Engkau memiliki keberanian yang
diwajibkan atas diri kita. Andai pada dirimu terdapat kekurangan dan
kekhilafan, kita akan mengobatinya. Pegang teguhlah agama dan pikiran yang
rasional, semua itu akan menopang dirimu dan menjadi kendali dirimu. Waspadalah
terhadap orang yang mencintaimu karena ada pamrih terhadap dirimu. Karena
manakala pamrih itu telah terpenuhi, cintanya akan sirna. Manakala engkau
melakukan suatu kebaikan, peliharalah betul kebaikan itu. Dan, jadikanlah dunia
sebagai tempatmu berpuasa dan akhirat sebagai tempatmu berbuka.’”
“Tuan Guru,
lanjutkanlah nasihatmu itu!”
“Abu ‘Umar
Salim bin ‘Abdullah kemudian tampil memberikan nasihat, ‘Amir Al-Mukminin!
Buatlah rakyat rela dengan sesuatu yang dirimu rela terhadap sesuatu itu. Juga,
buatlah mereka tidak menyukai sesuatu yang dirimu tidak menyukai sesuatu itu.
Dengan demikian, engkau selamatkan
mereka dan mereka menyelamatkan engkau.’”
Mendengar
nasihat dan petuah demikian, Harun Al-Rasyid pun tidak kuasa menahan lelehan
air matanya dan termenung lama.
Dan, selepas itu, dia berpamitan kepada sang Tuan Guru itu.
“Entah apa
yang saat ini sedang menggelegak dalam benak para menteri baru itu, ketika
mereka bersumpah akan melaksanakan amanah yang dibacakan Presiden. Wallâhu a‘lam,”
demikian gumam pelan bibir saya melihat prosesi sumpah yang dilakukan para
menteri baru itu.