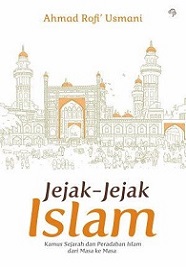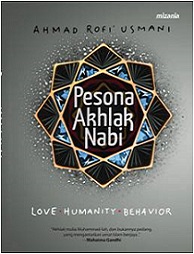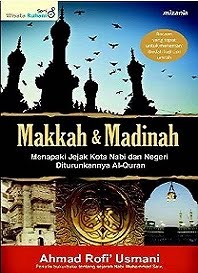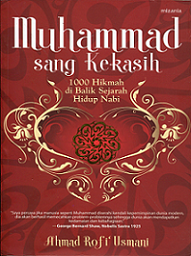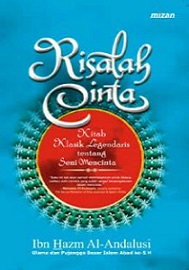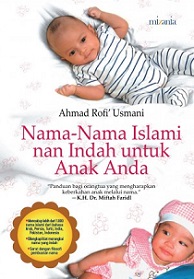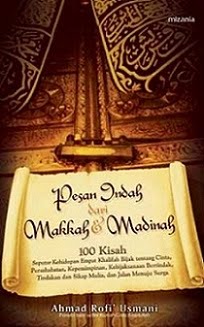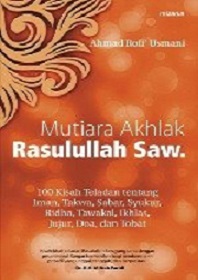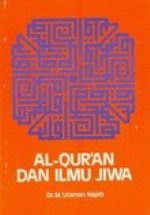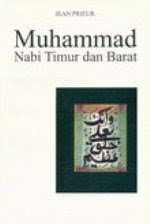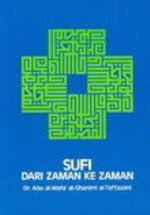PENSIUN:
Catatan Pengabdian Selama 30 Tahun kepada Masyarakat
“Mas, tadi saya diberitahu rumah sakit, mulai bulan depan
saya memasuki masa pensiun.”
Demikian ucap istri, sepuluh hari lalu, ketika dia baru
saja pulang dari tempatnya bekerja di sebuah rumah sakit di Baleendah,
Kabupaten Bandung. Wajahnya, kala itu, memancarkan antara perasaan sedih dan
gembira. Sedih, karena akan berpisah dengan tempatnya bekerja, dan gembira
karena dapat merampungkan tugasnya sebagai dokter spesialis tetap di rumah
sakit tersebut.
Mendengar ucapan istri yang demikian, segera benak saya
pun “melayang-layang” dan teringat perjalanan panjang karier istri sebagai
seorang dokter. Kami bertemu pertama kali 30 tahun yang lalu, ketika dia sedang
bertugas di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta. Beberapa bulan kemudian, kami
menikah. Seminggu setelah menikah, karena menerima perintah penempatan dari
Departemen (kini Kementerian) Kesehatan Republik Indonesia, istri dan saya pun
menuju Bandung dengan hanya membawa dua tas. Setelah melapor di Kantor Wilayah Departemen
Kesehatan Jawa Barat, dia ditempatkan di Kabupaten Bandung, untuk melaksanakan
Wajib Kerja Sarjana 1 di Kabupaten Bandung.
Setelah bertugas beberapa lama di Pusat Kesehatan
Masyarakat (Puskesmas) Cililin dan Ciparay, pada November 1984, dia ditugaskan
untuk menjabat Kepala Puskesma Pakutandang, Ciparay disertai perintah harus
tinggal di rumah dinas di puskesmas tersebut. “Mas, ternyata rumah dinas yang
akan kita tempati tidak ada listriknya. Itu belum apa-apa. Saya, bersama 12
staf yang belum berpengalaman, akan memulai kerja tanpa perabotan sama sekali
di sebuah puskesmas yang belum rampung pembangunannya. Kami akan mulai bekerja
hanya dengan tikar saja,” ucap istri seusai melihat kondisi puskesmas tersebut.
“Bismillah, laksanakan saja perintah itu dengan ikhlas
dan sebagai bentuk pengabdian kita kepada masyarakat,” jawab saya.
Bukan hanya dengan peralatan yang terbatas, namun juga
dana yang terbatas. Namun, semua itu tidak menghalangi dia untuk bekerja dengan
sebaik-baiknya. Dan, lewat pengabdian selama sekitar enam tahun di puskesmas
tersebut, kami mendapat pengalaman yang sangat berharga: ketika kita mengabdi
kepada masyarakat dengan ikhlas, kerja keras, dan jujur, masyarakat pun tahu
apa yang kita lakukan dan menghargai pengabdian kita serta dengan senang hati mereka
membantu kita. Karena itu, tidak aneh jika dalam waktu enam tahun, Puskesmas
Pakutandang beralih dari strata paling “bontot”, alias strata 3, menjadi
puskesmas strata 1, alias puskesmas teladan, tanpa perlu melakukan tindakan
manipulatif apa pun. Setiap hari kerja, puskesmas itu dihadiri tidak kurang
dari 300 pasien.
Sebelum kami meninggalkan puskesmas yang menjadi tempat
kelahiran dua putri kami tersebut, kami mendapatkan kenangan indah: kami mendapat
hadiah gambar sebuah masjid mungil dari seorang arsitek maestro Indonesia, Ir.
Achmad Noe’man (seorang arsitek yang merancang Masjid Salman ITB, Bandung) dan
membangun sebuah masjid mungil sesuai gambar tersebut di lingkungan puskesmas
dengan luas lahan terluas di Kabupaten Bandung: 4,000 meter persegi. Dan, atas
pengabdiannya tersebut, istri mendapatkan penghargaan dengan ditunjuk sebagai
anggota Tim Kesehatan Haji Indonesia.
Pada Mei 1990 kami pindah ke Kota Bandung, dengan diantar
tidak kurang dari 70 masyarakat Pakutandang.
Dengan berat hati kami meninggalkan Desa Pakutandang, karena istri
mengikuti pendidikan dokter spesialis penyakit dalam di Universitas Padjajaran.
Enam tahun setelah mengikuti pendidikan yang tidak mudah (antara mengurus rumah
tangga dan mengikuti pendidikan yang berat), akhirnya pada 1996 pendidikan itu
terselesaikan. Kemudian, ketika melapor ke Departemen Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta,
untuk membayar utang, alias melaksanakan Wajib Kerja Sarjana 2, apa yang
terjadi? Ucap seorang pejabat di departemen tersebut, “Silakan dokter memilih, mau
berangkat ke Irian Jaya, Maluku, Nusa Tenggara Timur, atau Nusa Tenggara Barat.
Di tempat-tempat tersebut, dokter akan ditempatkan selama satu tahun. Jika
memilih ditempatkan di Jawa, dokter harus mengabdi selama lima tahun, untuk
bisa mendapatkan surat lolos butuh. Kami memberikan kesempatan kepada dokter
untuk memikirkannya dalam waktu sehari semalam!”
Akhirnya, kami memilih mengabdi di Nusa Tenggara Barat,
dengan penempatan di Kota Bima. Dengan meninggalkan dua putri di Bandung
(mereka baru menempuh pendidikan di sekolah dasar), kami pun berangkat ke
Mataram, untuk melapor penempatan istri, ke Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Seusai melapor, ucap istri kepada
saya, “Mas, saya harus “babat alas” lagi. Saya tidak jadi ditempatkan di Bima.
Tapi, saya ditempatkan di Praya, ibu kota Lombok Tengah. Kota itu telah
memiliki Rumah Sakit Umum Daerah. Sayangnya, sampai saat ini tidak ada dokter spesialis
penyakit dalam yang mau ditempatkan di rumah sakit tersebut. Kabupaten Lombok
Tengah, saat ini, merupakan kabupaten termiskin di Nusa Tenggara Barat.
Bagaimana enaknya?”
“Bismillah, lakukan saja tugas itu,” jawab saya.
Sekali lagi, pelajaran serupa kami dapatkan ketika istri
bertugas di Praya: : ketika kita mengabdi kepada masyarakat dengan ikhlas,
kerja keras, dan jujur, masyarakat pun tahu apa yang kita lakukan dan
menghargai pengabdian kita serta dengan senang hati mereka membantu kita.
Awal tahun 1998, ketika Indonesia menjelang “dihajar”
krisis ekonomi, dan beberapa bulan sebelum Pak Harto lengser, istri kembali ke
Bandung setelah rampung “membayar utang”, alias melaksanakan Wajiba Kerja
Sarjana 2, di Praya. Setiba kembali di Bandung, sebagai Pegawai Negeri dengan
pangkat IIId, sebuah rumah sakit Islam mengharapkan istri bertugas di situ,
dengan syarat melepaskan kedudukannya sebagai pegawai negeri. Kala itu, tidak
ada dokter spesialis penyakit dalam yang mau menerima persyaratan demikian untuk
ditempatkan di rumah sakit tersebut. Syarat keluar dari pegawai negeri itu
diperlukan rumah sakit tersebut untuk melengkapi perizinannya. “Mas, masa saya
harus “babat alas” melulu. Bagimana ini enaknya?”
“Keluar saja dari pegawai negeri. Rezeki Allah Swt. yang
mengatur. Kalau tiada yang mau memenuhi syarat demikina, kapan rumah sakit itu
memiliki izin,” jawab saya.
Akhirnya, istri pun melepaskan kedudukannya sebagai
pegawai negeri. Dan, sejak itu, dia bertugas di Rumah Sakit Al-Ihsan (kini
menjadi sebuah rumah sakit umum daerah di bawah pemerintah Provinsi Jawa
Barat), dengan sederet tugas, antara lain sebagai wakil direktur (dua kali),
Ketua SMF Penyakit Dalam, Ketua Komite Infeksi, Ketua Komite Kendali Mutu dan Etik, dan pemrakarsa
berdirinya Diabetic Center, sampai akhirnya menerima keputusan pensiun bulan
depan. Semoga amal dan pengabdiannya kepada masyarakat diterima Allah Swt.,
amin ya Rabb Al-‘Alamin.