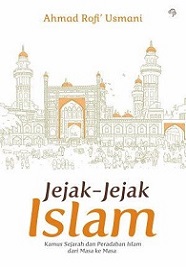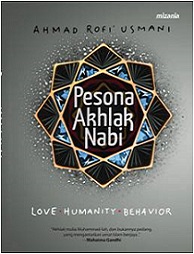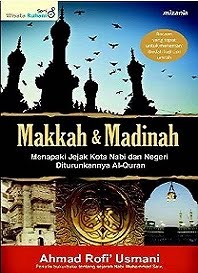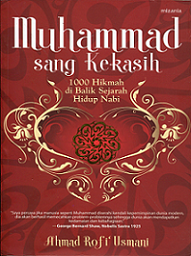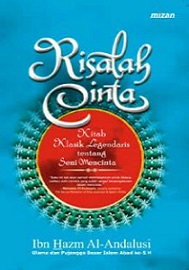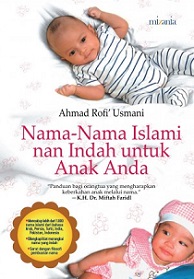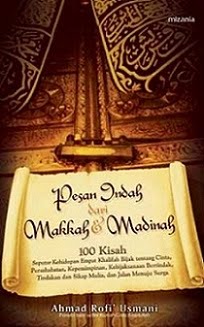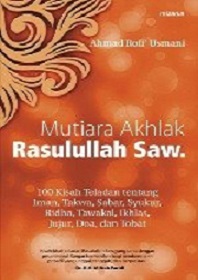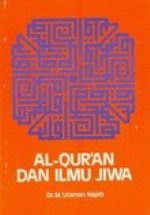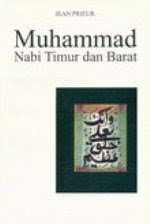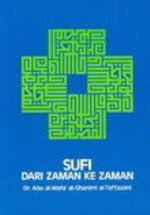SUAMIKU, TEGAKAH ENGKAU MENINGGALKAN KAMI?
Betapa pedih dan perih hati Nabi Ibrahim a.s. ketika menyadari kegagalan
misinya di tempat kelahirannya. Kemudian, ketika kian menyadari bahwa kesempatan
menyampaikan seruannya yang sangat terbatas di Babylonia, Nabi Ibrahim a.s.,
yang kala itu telah menikah dengan Sarah, lantas meninggalkan tanah airnya.
Kini, pandangannya terarah ke Haran, suatu wilayah yang terletak di
bagian utara Semenanjung Arab. Jauh dari tanah kelahirannya.
Dengan diam-diam Nabi Ibrahim a.s. pun meninggalkan tanah airnya. Sang
Nabi, menurut Dr. Shauqi Abu Khalil dalam sebuah karyanya berjudul Atlas of
the Qur’an, berhijrah ke Haran bersama istrinya dan Luth, juga
seorang Nabi, yang juga disertai istrinya. Di sana, mereka menemukan penduduk
yang menyembah bintang. Dan, ternyata,
seperti halnya penduduk Babylonia, penduduk Haran pun menolak seruan
Nabi Ibrahim a.s. Karena itu, di Haran sang Nabi dan rombongannya
tinggal hanya beberapa lama. Sang Nabi, istrinya, Nabi Luth, dan juga istrinya,
kemudian menuju Palestina. Namun, karena kondisi Palestina kala itu sedang
paceklik, mereka lantas melanjutkan perjalanan mereka ke arah barat, menuju
Mesir.
Mudahkah perjalanan jauh Nabi Ibrahim a.s. dan rombongannya itu?
Tentu saja tidak mudah. Sebagai perbandingan, hingga pada tahun 1930-an,
sekitar 3.900 tahun selepas masa Nabi Ibrahim a.s., perjalanan dari Mali,
sebuah negara di Afrika, menuju Makkah, masih demikian sulit. “Enam tahun,
itulah waktu yang diperlukan ayah ketika berziarah ke Makkah pada tahun
1930-an,” demikian tulis Jean Couteau dalam tulisannya berjudul “Lagu Para
‘Griot’ dari Afrika” (Kompas, 27 Januari 2013), mengutip penuturan
Daouda, bekas asisten ayah Jean Couteau. “Dari Segou ke-10 peziarah itu
mencapai Gao dengan menumpang perahu nelayan Bozo di Sungai Niger. Lalu masuk
wilayah tak dikenal, menuju Makkah, apakah dengan berjalan kaki atau dengan
naik unta, pertama sampai ke Danau Chad, lalu melalui Darfur, sampai ke
Omdurman dengan sungai Nilnya. Akhirnya, setelah melewati sungai raksasa itu,
sampai Port Sudan. Diperlukan waktu tempuh enam tahun pulang pergi. Di seberang
Laut Merah itu, terletak Tanah Suci, dengan tawaf dan Ka‘bah yang
dinanti-nantikannya. Dari sepuluh peziarah Segou dua tahun sebelumnya, tinggal
tujuh. Empat tahun kemudian, yang kembali tinggal lima. Yang lainnya hilang di
jalan, diculik suku Perazzia Songhai di Niger dan Arab di Sudan, atau meninggal
karena sakit.”
Di Mesir, sang Nabi dan Sarah tinggal di sekitar Memphis yang letaknya
tidak jauh dari Kota Kairo dewasa ini. Di Negeri Piramid itu, mereka berniaga,
bertani, dan beternak. Selama berada di Mesir, sang Nabi juga mendapat hadiah
seorang pelayan, Hajar, dari penguasa Mesir kala itu. Setelah beberapa
lama di Negeri Piramid, mereka kemudian kembali ke Palestina selatan. Di sini,
Nabi Luth a.s. dan istrinya berpisah dengan Nabi Ibrahim a.s. dan istrinya,
Sarah dan pelayannya, Hajar. Nabi Ibrahim a.s. dan keluarganya kemudian
menetap di B’ir Sheba (Al-Saba’). Sedangkan Nabi Luth a.s. dan istrinya
kemudian melanjutkan perjalanan dan kemudian menetap di wilayah selatan Laut
Mati. Di wilayah itu, Nabi Luth a.s. menyampaikan seruannya kepada penduduk
Sodom dan Gomorah.
Di sisi lain, setelah bertahun-tahun menikah, pasangan Nabi Ibrahim a.s.
dan Sarah tidak kunjung dikaruniai anak. Karena itu, untuk memeroleh keturunan,
Sarah pun mengizinkan suaminya untuk menikahi Hajar, pelayan mereka.
Dari perkawinan ini lahirlah kemudian Isma‘il, ketika Nabi Ibrahim a.s. berusia
sekitar 68 tahun. Ternyata, kehadiran Isma‘il, membuat rasa cemburu Sarah
kepada Hajar bersemi. Akhirnya, tidak tahan dengan rasa cemburu yang
kian membara itu, kemudian Sarah meminta sang suami tercinta agar memindahkan
Hajar beserta anaknya yang masih menyusu ke suatu tempat yang sangat jauh. Ya,
ke tempat yang sangat jauh, sehingga kuasa meredam rasa cemburu Sarah yang kian
lama kian membara.
Sejatinya siapakah Hajar, hingga Nabi Ibrahim a.s. berkenan
menikahinya dan dicemburui Sarah?
“Hajar,” jawab Dr. Ali Syariati dalam sebuah karyanya berjudul Hajj,
“adalah seorang perempuan miskin, budak Ethiopia yang dipandang rendah, dan
pelayan bagi Sarah. Semua ini menunjukkan kualifikasinya dalam sistem sosial
manusia-dalam sistem politeisme, tapi tidak dalam sistem monoteisme. Budak ini
adalah seorang penyeru Allah, ibunda para nabi yang utama, dan wakil
makhluk-makhluk Allah yang paling cantik dan disayang.”
Suatu pelajaran indah tergelar dalam kisah menawan ini: seorang Nabi
yang mendapat gelar “Khalil Allah” (Orang yang Dikasihi Allah) tidak segan
menikahi seorang perempuan dari strata yang paling rendah dalam masyarakat kala
itu: seorang budak hitam dari Ethiopia. Namun, meski berasal dari strata
masyarakat paling rendah, dia mendapatkan anugrah dari Allah Swt. sebagai
“penyeru Allah, ibunda para nabi yang utama, dan wakil para Allah yang paling
cantik dan disayang.” Indah sekali.
Atas wahyu dari Allah Swt., permintaan Sarah pun dipenuhi Nabi Ibrahim
a.s.: membawa pergi sangat jauh Hajar dan putranya. Sang Nabi kemudian
mengajak Hajar dan putranya, Isma‘il, menempuh perjalanan sangat jauh ke
tengah padang pasir yang kini menjadi
Kota Makkah, dekat sebuah bangunan suci yang kemudian dikenal sebagai Ka‘bah.
Di tempat yang kering kerontang itu, tanpa penghuni, sang Nabi meninggalkan
istri dan putranya yang masih kecil di atas Zamzam (sebuah tempat yang kemudian
tegak Masjidil Haram kini). Sang Nabi meninggalkan keduanya dengan bekal
hanya sekantung makanan dan minuman.
Kemudian, ketika Nabi Ibrahim a.s. dengan langkah-langkah yang sangat
berat meninggalkan istri dan putranya di tempat yang kering kerontang itu, sang
istri pun segera bangkit, memburunya, dan kemudian memegangi bajunya kuat-kuat
seraya berucap, “Wahai Ibrahim, suamiku. Tegakah engkau meninggalkan kami
berdua di tempat yang kering kerontang dan sangat sunyi ini, sedangkan kami
tidak memiliki perbekalan sama sekali?”
Suami manakah yang tidak perih hatinya mendengar ucapan sang istri yang
demikian. Mendengar ucapan yang demikian, Nabi Ibrahim a.s. tidak kuasa berucap
sepatah kata pun. Termenung dan mulutnya tersekat. Melihat sang suami tidak
menjawab, sang istri pun kemudian bertanya dengan suara lirih dan penasaran,
“Wahai Ibrahim, suamiku. Apakah Allah Swt. yang memerintahkan semua ini?”
“Ya,” jawab Nabi Ibrahim a.s. dengan suara sangat lirih seraya
menundukkan kepala.
“Bila demikian,” ucap penuh percaya diri Hajar, seperti dituturkan
Al-Bukhari dalam sebuah karyanya berjudul Shahîh Al-Bukhârî,
“tentu Dia tidak akan menyia-nyiakan kami. Silakan engkau kembali ke Bumi Kana‘an.”
Usai berucap demikian, Hajar kemudian memeluk sang suami dan
menyilakan suaminya tercinta meninggalkan dirinya dan putranya yang masih
kecil, Isma‘il, di tempat nan kering kerontang dan sunyi itu. Nabi Ibrahim a.s.
pun menapakkan kedua kakinya. Tetap dengan langkah-langkah yang sangat berat.
Namun, perintah Sang Pemberi Perintah tetap dia laksanakan. Karena itu, ketika
langkahnya tiba di sebuah bukit (konon Bukit Abu Qubais atau Jabal Abu Qubais
yang kini menjadi Istana Kerajaan di samping Masjid Al-Haram), tidak
jauh dari tempat istri dan putranya dia tinggalkan, sang Nabi kemudian berhenti
beberapa lama dan berdoa dengan sepenuh hati,
“Ya Allah, Tuhan kami.
Sungguh, aku telah meninggalkan sebagian dari anak keturunanku di lembah yang
tidak terdapat tetumbuhan apa pun, di dekat Rumah-Mu yang dihormati. Ya Allah,
Tuhan kami. (Yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat. Karena itu,
jadikanlah sebagian hati manusia cenderung kepada mereka dan karuniakanlah
rezeki dari buah-buahan kepada mereka. Kiranya mereka senantiasa bersyukur.”
(QS Ibrâhîm [14]: 37).
Usai berdoa demikian, Nabi Ibrahim a.s. kemudian meninggalkan Hajar
dan Isma‘il di tempat kering kerontang itu, karena harus kembali ke Bumi
Kana‘an untuk menemui Sarah. Dalam perjalanan itu sang Nabi tidak
henti-hentinya berdoa: memohon keselamatan bagi istri dan putranya yang
ditinggalkannya di bumi nan kering kerontang itu. Di sisi lain, selepas
perbekalan yang ditinggalkan habis, Hajar bersusah payah mencari air. Atas pertolongan
Allah Swt., melalui Malaikat Jibril, tiba-tiba di dekat Isma‘il muncul sebuah
mata air yang bening. Dan, hingga kini, mata air itu dikenal dengan sebutan
Sumur Zamzam.
Beberapa tahun kemudian, Isma‘il yang telah beranjak menjadi remaja
menggembirakan hati Nabi Ibrahim a.s. Tetapi, suatu saat, kegembiraan sang
ayahanda yang telah lanjut usia itu tiba-tiba buyar. Lewat mimpi, Allah Swt.
memerintah sang Nabi agar anak kesayangannya itu disembelih. Mula-mula sang
Nabi sangat sedih menerima mimpi yang demikian itu. Namun, sebagai orang yang
saleh dan taat, dia berniat melaksanakan perintah Allah Swt. itu dan kemudian
menyampaikan berita itu kepada putranya. Ternyata, tanpa ragu-ragu sang putra
meminta sang ayahanda untuk melaksanakan perintah itu. Akhirnya, ketika
perintah itu dilaksanakan, Allah Swt. mengganti Isma‘il dengan seekor domba.
Kemudian, ketika Nabi Ibrahim a.s. berusia 90 tahun, datang perintah
dari Allah Swt. agar sang Nabi mengkhitan dirinya sendiri, Isma‘il, putranya
yang ketika itu berusia 13 tahun, dan seluruh anggota keluarganya.
Selain itu, suatu saat, Nabi Ibrahim a.s. menerima kabar gembira dengan
kehamilan Sarah. Menurut kabar gembira tersebut, sang putra dari perkawinan
sang Nabi dengan Sarah itu, seperti halnya Isma‘il, juga akan menjadi seorang
Nabi yang saleh (lihat QS Al-Shaffât [37]: 112-0113).Tentu, kabar gembira itu
disambut sang Nabi dan istrinya, Sarah dengan penuh rasa suka cita yang
diwarnai seribu tanda tanya. Pekik Sarah, ketika menerima kabar gembira itu,
penuh rasa gembira dan tidak percaya, “Sungguh mengherankan! Apakah aku akan
melahirkan anak? Padahal, aku adalah seorang perempuan tua, dan ini suamiku pun
sudah dalam keadaan tua pula? Sungguh, ini merupakan hal yang benar-benar
sangat aneh.” (QS Hûd [11]: 72).
Tentu saja Nabi Ibrahim a.s. dan Sarah terkaget-kaget dan keheranan
menerima kabar gembira yang aneh itu. Kala itu, mereka telah lanjut usia.
Namun, tiada yang mustahil bagi Allah Yang Maha Kuasa. Jawab malaikat yang
membawa kabar gembira atas pertanyaan mereka berdua, “Apakah kalian merasa
heran atas ketetapan Allah? (Itu merupakan) rahmat Allah dan keberkahan-Nya
yang dikaruniakan kepada kalian, wahai ahlul bait. Sungguh, Allah Maha Terpuji
lagi Maha Pemurah.” (QS Hûd [11: 73).
Ya, tiada yang mustahil bagi Allah Yang Maha Kuasa: suatu pelajaran
indah tentang kekuasaan Sang Pencipta. Dan, kemudian, sesuai dengan kabar
gembira tersebut, lahirlah sang putra yang sangat dinantikan kehadirannya oleh
kedua orang tuanya.
Di sisi lain, selain menerima kabar gembira tersebut, “Ayah Para Nabi”
yang nenek moyang bangsa Arab dan Israel itu juga menerima perintah untuk
membangun Rumah Allah (Bait Allâh) di Makkah. Segera, sang Nabi pun
pergi ke Makkah. Kemudian, bersama putranya yang telah tumbuh dewasa, sang Nabi
pun membangun Ka‘bah. Dan, ketika pembangunan Rumah Allah itu usai, mereka
berdua kemudian berdoa, “Ya Allah, Tuhan kami. Terimalah (amal dari) kami
(ini). Sungguh, Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ya Allah,
Tuhan kami. Jadikanlah kami berdua orang-orang yang tunduk patuh kepada-Mu dan
(jadikankanlah) di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada-Mu serta
tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat ibadah haji kami, dan terimalah
tobat kami. Sungguh, Engkau adalah Zat Yang Maha Penerima toba lagi Maha
Penyayang.” (QS Al-Baqarah [2]: 128-129).
Usai melaksanakan perintah mulia itu, Nabi yang tangguh dan
memiliki anak keturunan yang banyak
menjadi Nabi itu kemudian balik ke Palestina. Di sana, di Palestina, pulalah
sang Nabi menetap hingga berpulang. Konon, menurut Ibn Katsir dalam sebuah
karyanya berjudul Qashash Al-Anbiyâ’, sang Nabi berpulang dalam usia
antara 175 hingga 200 tahun. Jenazahnya dimakamkan di Gua Machpelah,
Al-Khalil (Hebron).
Nah, bila Anda berziarah ke Palestina, jangan lupa berkunjung ke Kota
Al-Khalil, sebuah kota yang terletak 30 kilometer di sebelah selatan Kota
Al-Quds Al-Syarif, alias Jerusalem. Di kota yang terletak di kawasan Tepi Barat
itu terdapat makam Kekasih Allah yang satu ini. Di makam itu, konon,
dikebumikan Nabi Ibrahim a.s. dan istrinya, Sarah, Nabi Ishaq a.s. dan
istrinya, Ribqah (atau Rebecca), dan Nabi Ya‘qub a.s. dan istrinya, Leah (Lia).