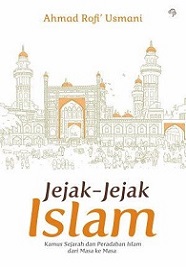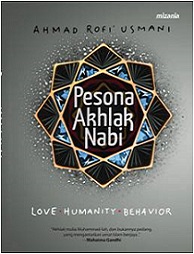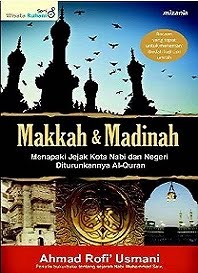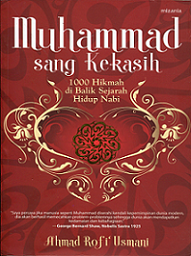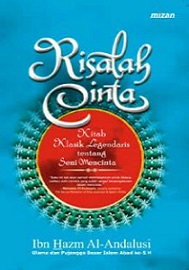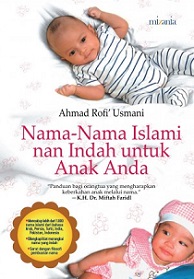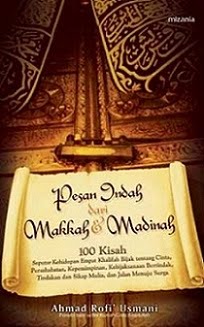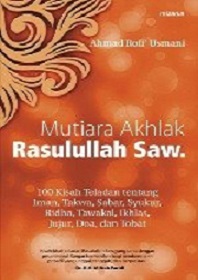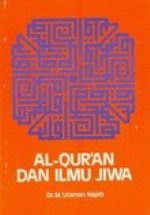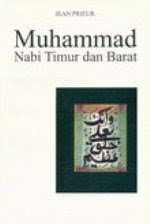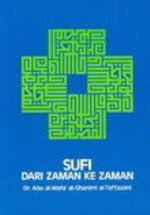+085.jpg) Dua hari selepas mengunjungi Maulid Al-Nabiy, penulis berkesempatan berziarah ke Gua Hira’. Gua yang terletak di Bukit Hira’ yang juga disebut Gunung Cahaya (Jabal Nûr) ini, seperti diketahui, terletak sekitar lima kilometer dari Masjid Al-Haram. Di gua inilah Rasulullah Saw., sebelum diangkat sebagai utusan Allah Swt., menyingkir dari keriuhrendahan kehidupan ramai di Kota Makkah kala itu. Kadang, beliau tinggal di sana selama satu bulan, lebih-lebih pada bulan Ramadhan. Hal yang demikian itu beliau lakukan selama sekitar tujuh tahun. Enam bulan terakhir beliau meningkatkan frekuensi kunjungannya ke gua itu. Peristiwa ini sendiri menandai dimulainya suatu karya kenabian, dengan diterimanya wahyu pertama dari Allah Swt. pada hari Senin, 17 Ramadhan yang bertepatan dengan 6 Agustus 610 M (menurut Ibn Sa‘d dalam karyanya Al-Thabaqât Al-Kubrâ), kala beliau sedang khusuk bertafakkur, “Bacalah, dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Paling Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.” (QS Al-‘Alaq [96]: 1-5).
Dua hari selepas mengunjungi Maulid Al-Nabiy, penulis berkesempatan berziarah ke Gua Hira’. Gua yang terletak di Bukit Hira’ yang juga disebut Gunung Cahaya (Jabal Nûr) ini, seperti diketahui, terletak sekitar lima kilometer dari Masjid Al-Haram. Di gua inilah Rasulullah Saw., sebelum diangkat sebagai utusan Allah Swt., menyingkir dari keriuhrendahan kehidupan ramai di Kota Makkah kala itu. Kadang, beliau tinggal di sana selama satu bulan, lebih-lebih pada bulan Ramadhan. Hal yang demikian itu beliau lakukan selama sekitar tujuh tahun. Enam bulan terakhir beliau meningkatkan frekuensi kunjungannya ke gua itu. Peristiwa ini sendiri menandai dimulainya suatu karya kenabian, dengan diterimanya wahyu pertama dari Allah Swt. pada hari Senin, 17 Ramadhan yang bertepatan dengan 6 Agustus 610 M (menurut Ibn Sa‘d dalam karyanya Al-Thabaqât Al-Kubrâ), kala beliau sedang khusuk bertafakkur, “Bacalah, dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Paling Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.” (QS Al-‘Alaq [96]: 1-5).Itulah saat penobatan Muhammad bin ‘Abdullah sebagai Nabi Allah. Saat menerima pengangkatan menjadi Nabi ini, usia beliau mencapai 40 tahun 6 bulan 8 hari menurut tahun Bulan (Qamariyyah) atau 39 tahun 3 bulan 8 hari menurun tahun Matahari (Syamsiyyah).
Di sini timbul pertanyaan: mengapa Rasulullah Saw. bertahannuts (menyendiri, merenung, dan beribadah) di Gua Hira’?
Tugas utama kenabian yang dipikul Rasulullah Saw., seperti diketahui, adalah untuk mengantarkan masyarakat menuju cita ideal yang dikehendaki Allah Swt. Tindakan menyendiri ke tempat yang sepi dan terpisah dari riuh rendah kehidupan masyarakat ramai tersebut sejatinya adalah sebagai persiapan untuk menerima dan melaksanakan tugas besar tersebut. Sebab, setiap tindakan besar yang hendak mengubah dan membentuk dunia sulit terjadi jika tidak ada seorang “agen” atau pribadi yang sadar dengan dua kemampuan sekaligus. Pertama, kemampuan untuk melakukan penjarakan terhadap kenyataan yang kongkrit (detachment). Dengan mengambil jarak atas kenyataan itu, seorang “agen” akan mampu melihat dunia dengan seluruh kekurangan, kelebihan, dan kemungkinan-kemungkinannya. Dunia tidak bisa diubah dan diantarkan menuju kemungkinan yang lebih baik, jika seorang “agen” tenggelam sepenuhnya dalam kepenuhan dunia itu sendiri. Kedua, kemampuan untuk terlibat kembali selepas momen penjarakan dilakukan beberapa saat (reattachment). Saat pengambilan jarak, atau dalam kasus Rasulullah Saw. disebut tahannuts, hanyalah situasi sementara agar seorang “agen” bisa berada di “luar” dunia. Saat terpenting justru berada kembali di “dalam” dunia untuk mengubah dan mentransformasikannya sesuai “gambar” yang dikehendaki seorang agen.
Al-Ghazali, dalam karyanya Ihyâ’ ‘Ulûm Al-Dîn, dalam komentarnya tentang jalan yang ditempuh Rasulullah Saw. ketika bertahannuts di Gua Hira’, menulis, “Manfaat pertama (dari bertahannuts) adalah pemusatan diri dalam beribadah, berpikir, mengakrabkan diri dalam munajat dengan Allah, dengan menghindari hubungan dengan sesama manusia, serta menyibukkan diri untuk menyingkapkan rahasia-rahasia Allah tentang persoalan dunia dan akhirat maupun kerajaan langit dan bumi. Inilah yang disebut kekosongan. Padahal, tiada kekosongan dalam bergaul serta mengisolasi diri. Mengisolasi diri jelas lebih baik. Malah, Rasulullah Saw., pada permulaan kenabian beliau, hidup menyendiri di Gua Hira’ serta mengisolasi diri, sehingga cahaya kenabian dalam diri beliau menjadi kuat. Ketika itu para makhluk tak kan kuasa menghalangi beliau dari Allah. Sebab, meski tubuh beliau beserta para makhluk, namun kalbu beliau senantiasa menghadap Allah.”
Pertanyaan lain yang mungkin timbul: mengapa Rasulullah Saw. memilih Gua Hira’ sebagai tempat bertahannuts, bukan tempat-tempat lain?
Gua Hira’, seperti diketahui, adalah sebuah gua yang terletak di sebelah timur Masjid Al-Haram dan di puncak Jabal Nur. Tingginya dari permukaan laut sekitar 621 meter dan sekitar 281 meter dari permukaan tanah. Untuk mendaki sampai ke gua itu diperlukan waktu kurang lebih satu jam. Gua itu sendiri tidak terlalu besar dan pintunya menghadap ke arah utara. Panjang gua tersebut hanya tiga meter, sedangkan lebarnya sekitar 1.30 meter, dengan ketinggian sekitar dua meter. Dengan kata lain, luas gua yang satu ini hanya cukup untuk shalat dua orang, sedangkan di bagian kanan Gua terdapat teras dari batu yang hanya cukup untuk digunakan shalat untuk shalat dalam keadaan duduk.
Kondisi Gua Hira’ yang demikian itu jelas merupakan tempat yang ideal di Makkah bagi Rasulullah Saw. untuk bertahannuts. Suasana yang tenang, jauh dari keriuhan Kota Makkah kala itu, dengan jumlah warganya sekitar 5.000 orang, pandangan yang terbuka ke tempat-tempat di bawahnya, terutama pandangan ke arah Masjid Al-Haram, dan pandangan ke padang pasir luas dan langit nan seakan tanpa batas, dapat dibayangkan dapat memberikan kesempatan bagi beliau untuk “beribadah, berpikir, mengakrabkan diri dalam munajat dengan Allah, dengan menghindari hubungan dengan sesama manusia, serta menyibukkan diri untuk menyingkapkan rahasia-rahasia Allah tentang persoalan dunia dan akhirat maupun kerajaan langit dan bumi” seperti dikemukakan Al-Ghazali.
Rasulullah Saw. sendiri, yang kala itu merupakan warga Kampung Qusyairiyyah, tentu telah mempertimbangkan matang pemilihan Gua Hira’ sebagai tempat bertahannuts. Beliau tentu telah memperbincangkan tempat itu dengan istri teladan beliau, Khadijah binti Khuwailid. Malah istri teladan beliau tersebut, di malam yang pekat, pernah beberapa kali mengunjungi Rasul Saw. ketika beliau sedang berada di Gua yang tak semua orang kuasa melakukannya itu, dengan menyusuri batu cadas dan kerikil, dengan tujuan agar dapat melayani sang suami tercinta dengan baik. Luar biasa. Istri yang pengusaha besar mana yang dengan tulus dan ikhlas mau melakukan seperti yang dilakukan Khadijah binti Khuwailid itu?
Di sisi lain ada yang menyatakan, Gua Hira’ adalah sebuah masjid sebelum Islam. Prof. Dr. Husain Mu’nis, seorang pakar terkemuka sejarah Islam asal Mesir, misalnya dalam karyanya Al-Masâjid menulis, “Pada umumnya para penulis memulai sejarah masjid dari Masjid Al-Haram, yaitu Rumah Allah pertama yang didirikan untuk umat manusia. Selain itu, masjid tersebut juga sebagai kiblat Ibrahim a.s., Bapak Para Nabi yang menganut agama yang hanîf, dan masjid di mana untuk pertama kalinya Rasulullah Saw. melaksanakan shalat. Namun, semestinya kita merujukkan masjid ke Gua Hira’. Gua itulah sejatinya, tak pelak lagi, masjid yang pertama-tama dalam Islam. Di Gua itu pulalah Rasul Saw. melaksanakan shalat, bertahannuts, dan menyembah Allah sebelum beliau menerima wahyu. Demikian halnya di Gua itu pulalah ayat-ayat pertama Al-Quran, lima ayat pertama dari Surah Al-‘Alaq, turun. Selain itu, Gua Hira’ juga semestinya dipandang sebagai masjid, meski kehadirannya mendahului masa masjid-masjid. Andaikan tidak tepat untuk dikatakan bahwa Rasul Saw. telah bersujud di Gua tersebut, selayaknya Gua tersebut dapat dikatakan sebagai tempat sembahyang. Seperti diketahui, masjid dapat disebut sebagai tempat sembahyang, seperti halnya pula dapat disebut sebagai tempat ruku‘. Namun, istilah masjidlah yang lebih acap dipakai.”