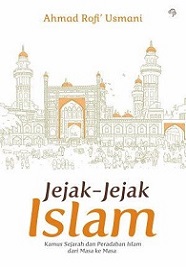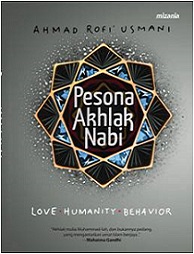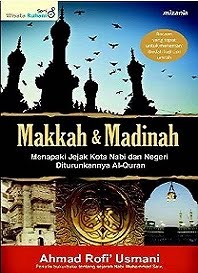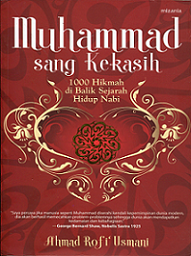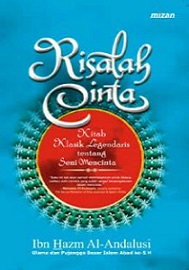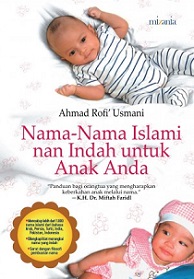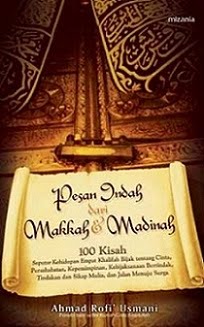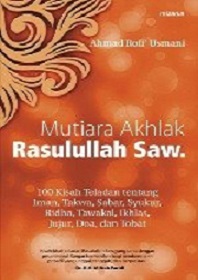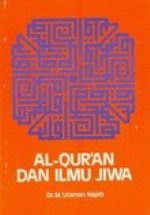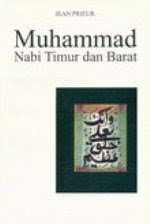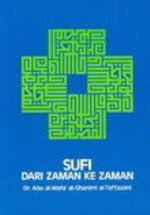“Kenapa sih para penguasa zaman dulu suka mendirikan benteng? Coba bayangkan, seperti Tembok Besar China itu, berapa besar dana yang dihamburkan?” tanya istri tercinta seraya memandangi Benteng Qait Bey yang terletak di tepi Laut Tengah. Hari di jam tangan saya saat itu masih menunjuk hari Jumat, 23 Maret 2007.
“Kenapa sih para penguasa zaman dulu suka mendirikan benteng? Coba bayangkan, seperti Tembok Besar China itu, berapa besar dana yang dihamburkan?” tanya istri tercinta seraya memandangi Benteng Qait Bey yang terletak di tepi Laut Tengah. Hari di jam tangan saya saat itu masih menunjuk hari Jumat, 23 Maret 2007.“Setiap benteng, baik benteng dalam bentuk bangunan fisik maupun benteng psikis, pada dasarnya merupakan perlindungan diri, sikap waspada, atau perlindungan dari rasa takut. Nah, benteng ini juga demikian. Sejatinya, benteng ini juga sebagai bentuk perlindungan diri Dinasti Mamluk dari kemungkinan serangan Dinasti Usmaniyyah dan juga sebagai saksi bisu runtuhnya dua dinasti, Dinasti Mamluk dan Dinasti ‘Abbasiyyah, serta lahirnya seorang maharaja tiga benua yang sangat disegani dan ditakuti pada abad ke-16 M. Sang maharaja tersebut tidak lain adalah Sultan Salim I. Sejatinya, tidak hanya para penguasa zaman dulu saja yang suka mendirikan benteng. Para penguasa zaman modern pun suka. Lihat saja penguasa Israel saat ini. Tembok yang dibangun di Palestina oleh Israel tersebut sejatinya kan juga benteng,” jawab saya seraya mengingat-ingat sejarah Dinasti Mamluk dan Dinasti Usmaniyyah.
“Mengapa demikian? Sebenarnya, siapa sih Qait Bey dan Salim I itu?” tanya lebih lanjut istri saya yang memang suka bertanya.
“Kalau begitu saya bercerita tentang kedua penguasa Muslim itu saja ya,” jawab saya. “Tentang sejarah benteng yang didirikan pada 1480 M ini, biar saja orang lain yang bercerita ya.”
Qait Bey tidak lain adalah seorang sultan dari Dinasti Mamluk Burji yang menguasai Mesir dan Suriah. Bergelar lengkap Al-Malik Al-Asyraf Abu Al-Nashr Saif Al-Din Al-Mahmudi Al-Zhahiri, ia memerintah antara 873-902 H/1468-1496 M. Lahir dengan tahun kelahiran yang tak jelas, ia melewati masa kecilnya sebagai seorang budak belian yang kemudian dibeli orang nomor satu Dinasti Mamluk kala itu, Al-Asyraf Saif Al-Din Barsbay, dan dimerdekakan oleh Al-Zhahir Saif Al-Din Jaqmaq yang juga orang nomor satu dinasti itu setelah Barsbay dan Yusuf. Selepas itu ia meniti karier di bidang militer. Sehingga akhirnya, pada 872 H/1467 M, ia diangkat sebagai atabeg oleh Al-Zhahir Temirbugha, orang nomor satu Dinasti Mamluk kala itu. Tahun berikutnya ia diangkat sebagai pengganti Temirbugha yang mangkat.
Setelah naik tahta, Qait Bey dihadapkan pada dua tantangan besar. Pertama, menghadang gerak maju pasukan Dinasti Usmaniyyah yang mulai mengintai Mesir dan ingin sekali “memeluknya di pangkuannya”, dan Dinasti Ak Koyunlou dari Turki. Kedua, mengatasi masalah ekonomi yang memburuk akibat ditemukannya Tanjung Harapan oleh para petualang Eropa yang sedang memburu “harta karun” di Indonesia. Dalam persoalan yang pertama, meski ia berhasil menahan gerak maju pasukan Dinasti Usmaniyyah dengan menawan Pangeran Elbistan di Anatolia, namun pasukannya tidak berhasil mengalahkan pasukan Dinasti Ak Koyunlou di bawah pimpinan Uzun Hasan. Malah, pada 891 H/1486 M pasukan Dinasti Usmaniyyah berhasil mengalahkan pasukannya di Silisia. Akhirnya, pada 897 H/1491 M, dicapai perjanjian perdamaian dengan Dinasti Usmaniyyah. Kesepakatan itu memberi kesempatan kepada penguasa yang berkuasa hingga 902 H/1496 M ini untuk memperbaiki kondisi perekonomian negeri yang dipimpinnya dan membangun benteng. Namun, keberhasilan di bidang ekonomi tersebut masih belum mampu menyelamatkan Dinasti Mamluk dari gempuran pasukan Dinasti Usmaniyyah yang akhirnya melibas Dinasti Mamluk sekitar satu setengah dekade setelah ia mangkat pada 902 H/1496 M. Mengapa hal itu terjadi?
Keberhasilan pasukan Dinasti Mamluk dalam menghadang pasukan Dinasti Usmaniyyah ternyata tidak pernah dilupakan oleh Salim I, seorang penguasa terkemuka Dinasti Usmaniyyah di Turki. Sultan Turki yang satu ini adalah salah seorang putra pasangan suami-istri Sultan Bayazid II dan Gulbahar Sultan. Ia lahir di kota Amasya pada Senin, 5 Rabi‘ Al-Akhir 875 H yang bertepatan dengan 10 Oktober 1470 M. Ketika sang ayah menjadi orang nomor satu, ia diberi kepercayaan sebagai Gubernur Trabzon, Turki. Lantas ketika sang ayah gering menjelang kemangkatannya, sang ayah mengangkat Salim sebagai putra mahkota dengan membatalkan hak sang putra sulung, Ahmad, untuk menduduki jabatan itu. Inilah salah satu pemicu terjadinya perang saudara yang membara di Turki selepas berpulangnya sang ayah ke hadirat Allah pada 918 H/1512 M. Perang saudara ini dimenangkan murid seorang ulama terkemuka kala itu: Mevlana ‘Abdul Halim.
Akibat kekalahan Ahmad bin Bayazid II dalam perang saudara tersebut, kedua putranya: Murad dan ‘Ala’ Al-Din, pun menyelamatkan diri. Murad menyelamatkan diri ke Persia (dh Iran), meminta suaka kepada penguasa negeri itu kala itu: Syah Ismail, penguasa pertama Dinasti Shafawiyyah di Persia. Sedangkan ‘Ala’ Al-Din menyelamatkan diri ke Mesir, meminta perlindungan kepada Sultan Qanshauh Al-Ghuri, penguasa Dinasti Mamluk di Mesir selepas Sultan Qait Bey. Perlindungan yang diberikan kepada kedua kemenakannya tersebut merupakan salah satu pemicu bagi Sultan Salim I untuk menggempur dan menaklukkan Persia dan Mesir.
Persia mendapat hajaran dalam Perang Chaldiran yang terjadi pada Rajab 920 H/1514 M. Dalam perang tersebut, pasukan Dinasti Usmaniyyah di bawah pimpinan Salim I berhasil meluluhlantakkan pasukan Persia dan dengan penuh kemenangan memasuki Tabriz, ibukota Persia kala itu, sehingga membuat Syah Ismail melarikan diri. Dua tahun kemudian, tepatnya pada Jumada Al-Awwal 921 H/Agustus 1516 M, Mesir ganti mendapat gempuran dari pasukan Dinasti Usmaniyyah. Akibat kekalahan pasukan Mesir dalam perang di Dataran Maraj Dabiq, terutama karena mangkatnya Sultan Qanshauh Al-Ghuri, pasukan di bawah pimpinan Salim I kemudian berhasil merangsek masuk Hamah, Homs, Damaskus, Nablus, Al-Quds, Gaza, dan akhirnya Suez. Kemudian, dengan takluknya Sultan Thuman Bay pada tahun berikutnya, pasukan Dinasti Usmaniyyah pun berhasil menguasai seluruh wilayah Mesir, termasuk Alexandria. Keberhasilan tersebut mengukuhkan Dinasti Usmaniyyah sebagai negara muslim paling berjaya, dengan kekuatan militernya yang sangat tangguh, terutama pasukan kavaleri dan artilerinya yang mampu bergerak sangat cepat “bagaikan topan yang menderu sangat kencang dan menggilas apapun yang menghadangnya”, di Timur Tengah kala itu.
Seusai menaklukkan Negeri Piramid tersebut, penguasa yang selalu mencukur bersih janggutnya, berbeda dengan para pendahulunya yang membiarkan panjang janggutnya, ini kembali ke negerinya dengan “mengantongi” dua gelar: Sulthan Al-Barrain wa Khaqan Al-Bahrain (Sultan Dua Daratan dan Khaqan Dua Lautan) dan Hamiy Al-Haramain Al-Syarifain (Sang Pelindung Dua Tanah Suci yang Mulia), dengan membawa serta khalifah terakhir Dinasti ‘Abbasiyyah di Mesir, Al-Mutawakkil ‘Alallah, dan putra-putranya, ke Istanbul. Sejak itu Dinasti ‘Abbasiyyah dan Dinasti Mamluk di Mesir “tutup buku dari sejarah untuk selamanya”. Dan, sejak itu pula, sultan-sultan Turki Usmani menjadi satu-satunya khalifah di dunia Islam dan menjadi seorang maharaja tiga benua: Eropa, Asia, dan Afrika! Ya, tiga benua: Eropa, Asia, dan Afrika!
Lantas, sekembalinya penguasa yang menguasai bahasa Turki, Persia, dan Arab ini, dari penaklukan-penaklukan tersebut, ia mencurahkan perhatiannya untuk membangun negerinya dan kawasan-kawasan yang berada di bawah kekuasaannya dengan bantuan para ilmuwan, pakar, dan teknisi. Dan, pada Selasa, 28 Ramadhan 926 H yang bertepatan dengan 21 September 1520 M, ketika dalam perjalanan menuju Edirne, ia berpulang ke hadirat Sang Pencipta, dengan meninggalkan seorang putra: Sulaiman, dan empat putri: Hatice Sultan, Fatma Sultan, Hafsa Sultan, dan Syah Sultan. Ia digantikan putranya semata wayang: Sulaiman The Magnificent (Sulaiman Agung yang terkenal membuat gentar seluruh benua Eropa).
“Luar biasa! Sejarah Islam sebenarnya disiplin yang menarik sekali, ya! Sayang, sejarah Islam yang pernah saya pelajari, hanya berisi pelajaran yang tak menarik. Tapi, kita jalan-jalan dulu ya,” ucap istri saya. “Yuk,” jawab saya seraya menapakkan kaki ke arah Benteng Qait Bey, bersama istri, Mas Oyik, dan Mas Norman Muttaqin. Dan, sore harinya, selepas mengunjungi Istana Montazah, kami kembali ke Kairo dengan melintasi jalur padang pasir.


 Memandangi masjid megah dan indah yang satu ini (sayang kebersihan lingkungannya kurang diperhatikan), “indra keenam” saya segera menyatakan, para pengikut Tarikat Syadziliyyah masih aktif hingga dewasa ini. “Sayang, saya tidak banyak memiliki data (bila di antara para pembaca ada yang memiliki data sejarah masjid ini, saya akan sangat berterimakasih bila data tersebut dapat diemailkan ke saya) tentang sejarah masjid ini,” gumam saya memandangi masjid yang banyak dikunjungi orang itu, selain kami, termasuk dua pramugari asal Indonesia yang bekerja di Saudi Airlines. Namun, dari pandangan sekilas terhadap masjid tersebut, dapat dikatakan masjid ini memiliki gaya arsitektural seperti halnya kebanyakan masjid-masjid yang banyak bertebaran di Mesir. Bagaimana gaya arsitektural masjid-masjid ala Mesir? Insya Allah akan saya hadirkan dalam tulisan berikut di blog ini.
Memandangi masjid megah dan indah yang satu ini (sayang kebersihan lingkungannya kurang diperhatikan), “indra keenam” saya segera menyatakan, para pengikut Tarikat Syadziliyyah masih aktif hingga dewasa ini. “Sayang, saya tidak banyak memiliki data (bila di antara para pembaca ada yang memiliki data sejarah masjid ini, saya akan sangat berterimakasih bila data tersebut dapat diemailkan ke saya) tentang sejarah masjid ini,” gumam saya memandangi masjid yang banyak dikunjungi orang itu, selain kami, termasuk dua pramugari asal Indonesia yang bekerja di Saudi Airlines. Namun, dari pandangan sekilas terhadap masjid tersebut, dapat dikatakan masjid ini memiliki gaya arsitektural seperti halnya kebanyakan masjid-masjid yang banyak bertebaran di Mesir. Bagaimana gaya arsitektural masjid-masjid ala Mesir? Insya Allah akan saya hadirkan dalam tulisan berikut di blog ini.